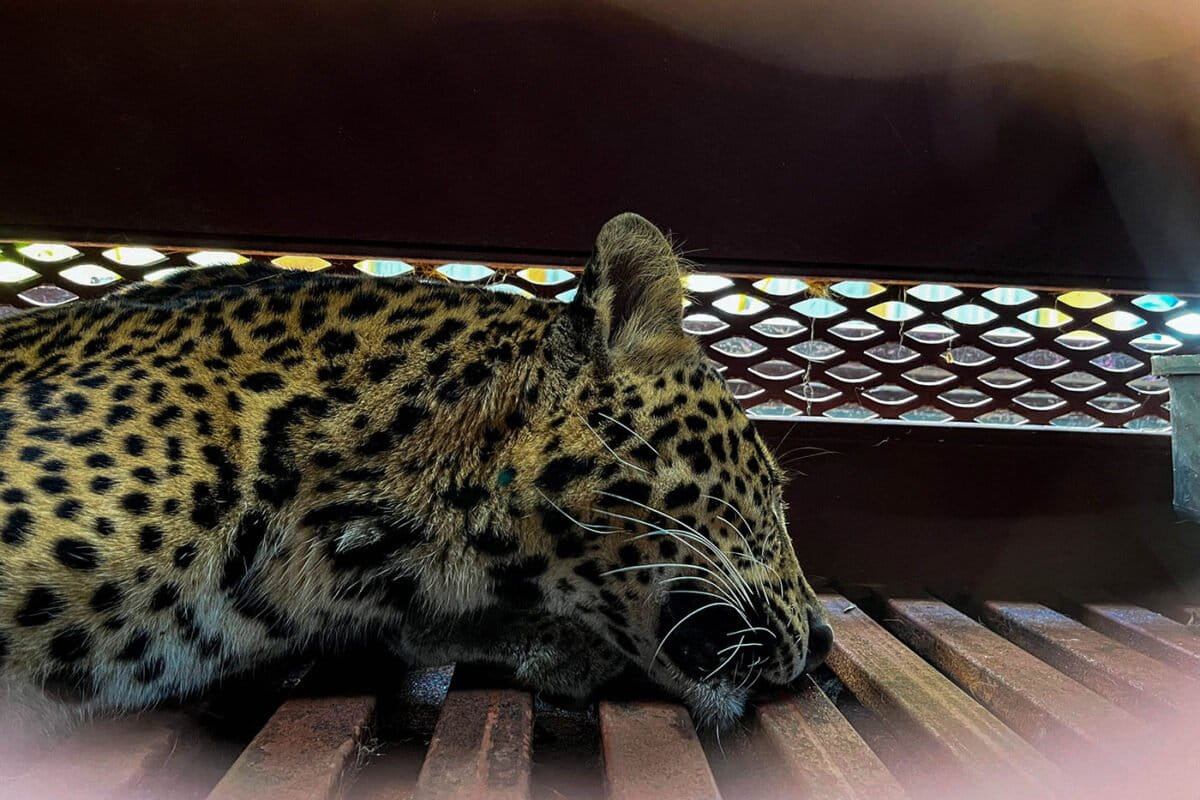- Pohon asam (Tamarindus indica L.) merupakan tanaman penting bagi masyarakat Desa Tapobali serta masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) secara umum.
- Dengan ragam pengetahuan dan tradisi pengolahan buah asam, masyarakat di Tapobali mampu bertahan dari sejumlah persitiwa gagal panen hingga kelaparan.
- Sejumlah bagian pohon asam, seperti daging buah, biji, hingga daun memiliki manfaat kesehatan yang baik bagi tubuh dan layak untuk dikembangkan sebagai pangan alternatif.
- Buah asam sudah menjadi komodias penting sejak zaman Hindia Belanda, dan NTT menjadi wilayah penghasil asam yang penting di Nusantara.
Mengupas serta memisahkan daging dari biji buah asam, merupakan aktivitas rutin yang dilakukan perempuan Suku Tobil, di Dusun Walet, Desa Tapobali, Kecamatan Wulandoni, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain kacang-kacangan dan pohon lontar, pohon asam merupakan satu dari sedikit tumbuhan yang bisa bertahan di Tapobali –lanskap permukiman pesisir dengan hamparan batu cadas di selatan Pulau Lembata.
Buah asam punya nilai penting bagi kehidupan mereka. Dari sejarah suku, hingga memori peristiwa gagal panen dan krisis pangan, semua terkait buah yang berasal dari pohon Tamarindus indica L. itu.
Patrisius Jengi, tokoh adat di Dusun Walet mengatakan, alasan dipilihnya Tanjung Walet sebagai tempat bermukim Suku Tobil karena keberadaan pohon asam dan pohon ara yang kini terletak di tengah kampung.
“Tidak tahu kenapa leluhur dulu memilih asam dan ara, sebagai simbol penting suku kami. Terlepas dari itu, keduanya punya peran penting bagi kehidupan kami,” kata Jengi, akhir Agustus 2025 lalu.
“Kalau ara, mungkin leluhur mau kasih tahu kita orang, penting untuk menjaganya di lahan sulit air seperti di Tapobali ini. Sementara pohon asam, memang sangat berguna bagi kami, hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan.”
Meskipun jumlahnya berkurang, diakui Jengi, pohon asam masih ditemukan di sekitar permukiman warga, kebun jagung atau sorgum, dan hutan sekitar lereng Gunung Ililabalekan.

Memasuki musim kemarau, pohon asam mulai berbuah dan siap dipanen pada rentang Agustus, September, dan Oktober. Dari tangan warga langsung, buah asam yang belum dipisahkan dari bijinya, dijual seharga Rp5.000 perkilogram. Sementara yang sudah dikupas, dihargai Rp10.000.
“Sebagian ada yang kami jual, sebagian lagi kami simpan jika sewaktu-waktu gagal panen,” kata Mama Lita, warga Dusun Walet.
Tinggal di lingkungan kering dan ekstrim, masyarakat Tapobali beberapa kali mengalami peristiwa kelaparan. Seingat Jengi, karena gagal panen, peristiwa itu terjadi pada 1969, 1971, 2003, 2011, dan 2014 lalu.
“Beruntung kami masih ada pohon asam. Saat gagal panen karena kemarau panjang, pohon asam tetap menghasilkan buah dan menjadi pangan penyelamat warga kala diterpa kelaparan.”
Mengkonsumsi biji asam, merupakan tradisi turun temurun masyarakat Tapobali. Bahkan, beberapa warga masih memakan biji asam ketimbang jagung.
“Kenyangnya lama, tidak mudah lapar,” kata Benedikta Ose, warga Dusun Walet, Desa Tapobali.
Buahnya yang mentah atau setengah matang, dimakan warga dengan garam dan lombok. Kadang ditambah gula air/lontar agar manis. Buah yang matang biasanya digunakan untuk membuat manisan, atau dikupas dan dikeluarkan bijinya lalu dibentuk seperti bola kecil untuk dijual dipasaran sebagai bumbu dapur.
“Sebagian ada juga yang disangrai, lalu direbus atau direndam air kurang lebih tiga jam. Biji asam yang siap dimakan, biasa dicampur nasi jagung dan lainnya.”

Kaya manfaat
Bagi sebagian orang, mengkonsumsi biji asam bukanlah hal lazim.
“Tapi, ratusan tahun masyarakat Tapobali makan biji asam, tidak ada dampak kesehatan yang dirasakan,” kata Ambrosia Ero, anggota Gebetan –sebuah komunitas pemuda yang sejak 2022 aktif melakukan gerakan pelestarian pangan lokal di Desa Tapobali.
Hampir semua bagian pohon asam bisa dimanfaatkan, mulai daun, buah, cabang ranting, hingga kulit batang. Semua dijelaskan dalam penelitian Pinto, (2025).
Biji asam kaya nutrisi, menjadikannya sumber pangan berharga. Kandungan utamanya meliputi makromolekul seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta senyawa pelindung seperti antioksidan.
Selain itu, biji asam mengandung beragam asam lemak, termasuk asam palmitat, asam oleat, dan asam linoleat. Biji asam juga berfungsi sebagai sumber penting dari berbagai mineral, yaitu zat besi, fosfor, potassium, magnesium, kalsium, dan sodium (Putri, 2014).
“Biji asam dapat dikonsumsi dan dijadikan sumber pasokan makromolekul, asam lemak dan mineral,” tulis penelitian tersebut.

Bagian daun juga memiliki beragam kegunaan, terutama sebagai bahan dasar pengobatan tradisional dan bumbu dapur. Masyarakat di Manatuto Vila, misalnya, memanfaatkan daun asam melalui metode dekoksi (merebus dalam air) untuk mengatasi berbagai penyakit seperti gatal, cacar air, demam, dan keputihan; ekstrak air rebusan ini digunakan untuk mandi dua kali sehari.
Hal yang sering dilakukan masyarakat di Tapobali. Pemanfaatan ini konsisten dengan praktik di Pagatan Besar, yang menggunakannya untuk cacar air, serta mengobati bisul dan menurunkan panas.
Bagian buah asam yang sering dimanfaatkan sebagai bumbu dapur juga memiliki sifat antiobesitas. Komponen fitokimianya mencakup alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan fenolik.
“Tamarindus indica L. bukan hanya memiliki nilai ekologis dan ekonomis, tetapi juga sosial-budaya yang penting. Pelestarian pengetahuan dan praktik etnobotani ini perlu didukung, untuk menjamin keberlanjutan identitas dan kesejahteraan masyarakat lokal,” tulis penelitian tersebut.

Sebagai informasi, dalam penelitian Wawo, (1998), menurut Purseglove (1968), pohon asam memiliki nilai guna beragam, seperti tanaman hias dan peneduh.
Batangnya yang keras, dimanfaatkan sebagai bahan baku arang. Dalam aspek pangan, biji asam dapat diolah, terutama di India. Setelah dikupas kulitnya, biji asam direbus atau digoreng kering untuk dikonsumsi (Burkill, 1935; PROSEA, 1992).
Biji asam juga dapat diproses menjadi tepung yang digunakan sebagai bahan dasar kue dan roti. Dari sisi perdagangan, asam dari Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya dari Pulau Timor, Maumere, Sikka, dan Flores, sudah menjadi komoditas penting sejak zaman Hindia Belanda (Heyne, 1987).
Pada masa itu, hasil panen asam dari NTT didistribusikan ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Hingga kini, Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama produksi asam dari NTT.
Referensi:
Pinto, A. (2025). Kajian Etnobotani Tanaman Asam (Tamarindus indica L.) Di Manatuto Vila Timor-Leste. Berkala Ilmiah Biologi, 16(2).
Wawo, A. H. (1998). Pengamatan Daya Hitoup Bui Asam Yang Berasal Dari Kotoran Ternak Sapi Dipadang Savana Besipae, NTT. Berita Biologi, 4(4), 62678.
*****