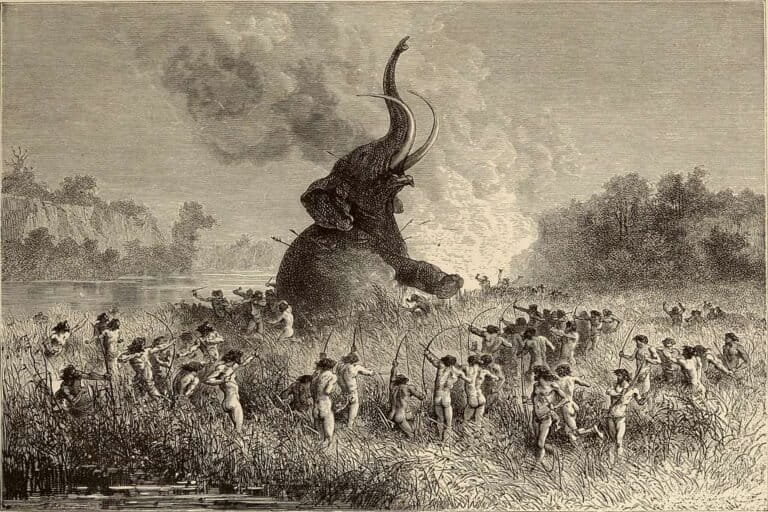- COP30 di Belem, Brazil memiliki sejarah dengan jumlah terbesar masyarakat adat yang hadir dari berbagai negara. Mereka menuntut pengakuan wilayah adat dan keadilan iklim yang penuh.
- Sayangnya, kesepakatan akhir dalam COP30 ini cukup mengecewakan bagi masyarakat adat. Pasalnya, komitmen iklim hanya dijalankan sebagai 'business as usual' yang tentu mengancam masyarakat adat.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai banyak kebijakan yang menjadi ancaman baru bagi masyarakat adat, seperti pasar karbon dan proyek transisi energi. Banyak kasus perampasan lahan, pencemaran hingga kriminalisasi masyarakat adat karena tidak merujuk pada hak masyarakat adat itu sendiri.
- Meski begitu, ada juga kesepakatan terkait upaya mempercepat pengakuan dan melindungi wilayah adatnya. Seperti, Intergovenmental Land Tenure Commintment, Belem Mechanism for Just Global Transition dan mekanisme pendanaan melalui Tropical Forest forever Facility, Forest Tenure Funders Group dan sebagainya.
Ada warna berbeda dalam Konferensi Tingkat Tinggi Iklim PBB (COP30) di Belem, Brazil. Kehadiran masyarakat adat mencapai jumlah terbesar sepanjang sejarah COP. Ribuan orang dari komunitas adat, kelompok muda, dan aktivis dari berbagai negara juga melakukan aksi dan menyerukan tindakan nyata dan penghentian kekerasan terhadap masyarakat adat.
Baik di ruang negosiasi maupun area luar, organisasi serta koalisi masyarakat adat terus menuntut keadilan iklim melalui pengakuan hak atas tanah serta mekanisme pendanaan yang adil bagi komunitas. Apalagi mereka menjadi garda terdepan dalam upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim. Relasi mereka dengan alam pun membuat mereka menjadi kelompok rentan terdampak dari krisis iklim secara langsung.
Perwakilan Indonesia, Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Fransiska Rosari Clarita You, perwakilan muda dari wilayah adat Papua juga turut bersuara dan melakukan aksi dalam COP30. Sayangnya, mereka menilai hasil COP30 belum mengakomodir penuh perlindungan dari masyarakat adat.

Pembentukan Belem Mechanism for Just Global Transition menjadi upaya memastikan transisi menuju ekonomi berkelanjutan berjalan adil, setara dan inklusi. Meski hal ini sudah pernah ada dalam COP27 di Mesir terkait Just Transisiton Work Programme (JTWP) untuk membimbing negara-negara menuju capaian iklim secara adil dan setara, kini secara eksplisit merujuk pada hak-hak masyarakat adat dengan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
Bagi organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), penyebutan eksplisit ini merupakan langkah maju karena untuk pertama kalinya muncul langsung dalam keputusan resmi COP.
“Hak itu hanya bermakna kalau negara menghormati batas wilayah adat dan tidak lagi mengeluarkan izin tanpa persetujuan kami,” kata Rukka Sombolinggi kepada Mongabay Indonesia.
Rukka menilai banyak kebijakan yang menjadi ancaman baru bagi masyarakat adat, seperti pasar karbon dan proyek transisi energi. Banyak kasus perampasan lahan, pencemaran hingga kriminalisasi masyarakat adat karena tidak merujuk pada hak masyarakat adat itu sendiri.
Seperti, kasus tambang nikel di Halmahera, Maluku Utara, pembangkit listrik panas bumi di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur dan kasus hutan energi sebagai upaya deforestasi.
Yuk, segera follow WhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan berita terbaru setiap harinya.
Pendanaan iklim yang berkeadilan bagi masyarakat adat

Intergovernmental Land Tenure Commitment menjadi salah satu capaian dalam COP30. Secara resmi, komitmen bersama dengan 14 negara dan satu negara bagian menyatakan dukungan untuk mengakui hak tenurial masyarakat adat hingga 160 juta hektar di negara-negara hutan tropis. Ini menjadi kesepakatan penting untuk perlindungan bagi masyarakat adat.
Khusus Indonesia, Rukka bilang pemerintah berkomitmen menetapkan 1,4 juta hektar hutan adat. Secara resmi, angka ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengakui 33,7 juta hektar wilayah adat yang telah dipetakan AMAN.
Selain itu, Forest Tenure Funders Group (FTFG) mengumumkan komitmen baru selama lima tahun senilai USD 1,8 Miliar untuk mendukung masyarakat adat dan komunitas lokal. Rukka menyebutkan akses pendanaan langsung ini masih terkendala di banyak negara, termasuk Indonesia. Ini karena pengakuan wilayah adat masih tersendat dan tidak adanya mekanisme yang memungkinkan komunitas menerima pendanaan tanpa perantara.

Studi terbaru Earth Insight dan Global Alliance of Territorial Communities menyebutkan masyarakat adat dan komunitas lokal menghadapi ancaman industri yang kian meningkat. Di Indonesia, 18% (6 juta hektar) wilayah adat tumpang tindih dengan konsesi kayu, 5% (1,6 juta hektar) dengan tambang minyak dan gas, dan hampir 1 juta hektar dengan operasi pertambangan. Di Halmahera misalnya, penambangan nikel mengancam ruang hidup masyarakat adat O’Hongana Manyawa.
Tak hanya itu, Tropical Forest Finance Facility (TFFF) resmi rilis pada COP30. Banyak pihak menyambut baik karena ini mendorong konservasi dan perluasan hutan tropis. Melalui pembayaran tahunan sebesar USD 4 per hektar kepada negara2 yang memiliki hutan tropis.
Meski begitu, inisiatif ini juga bisa berpotensi menjadi modus greenwashing. Apalagi, alokasi pendanaan tersebut hanya 20% untuk masyarakat adat dan 80% dalam kendali negara.
(*****)