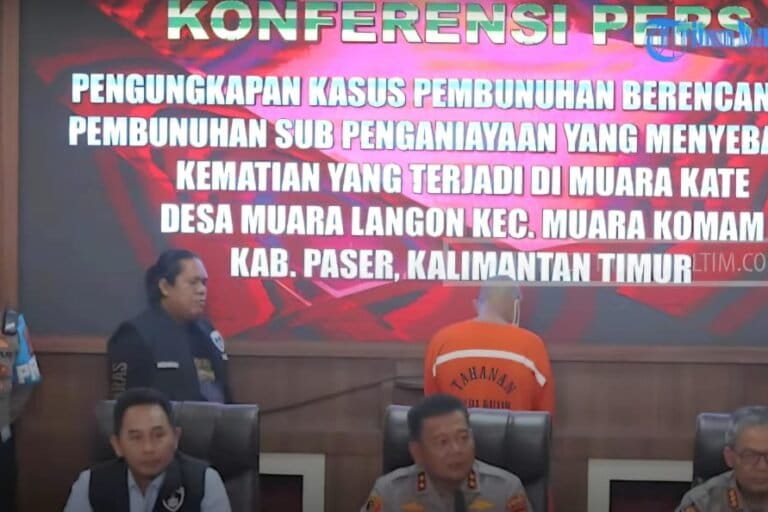- Ketika hutan yang jadi ruang hidup Orang Rimba di Jambi, tergerus, pemerintah berupaya bangunkan pemukiman. Kini, mereka hidup serba terbatas, sebagian mencari berondolan sawit. Ada juga yang berkebun di lahan sempit atau piara sapi.
- Hutan hilang, sumber segala pun lenyap dari sumber makanan, obat-obatan maupun berbagai tradisi budaya Orang Rimba.
- Yudi, Tumenggung Komunitas Orang Rimba di Pelakar Jaya, sedih memikirkan nasib anak-anak mereka yang tidak mempunyai ruang hidup, mata pencaharian yang bergantung pada berondol sawit, dan dianggap beban pemerintah atau masyarakat lain.
- Eko Cahyono, peneliti agraria dan sosiologi perdesaan di Sajogyo Institut, mengatakan, peralihan masyarakat pemburu-peramu menjadi masyarakat agraris yang menetap setidaknya 200-250 tahun. Perubahan drastis strategi bertahan hidup suatu masyarakat bukanlah hal mudah karena mereka terbiasa mengambil kebutuhan dari alam, dan mengandalkan alam apa adanya.
Sekitar 20 rumah berhadap-hadapan di Desa Pelakar Jaya, Kecamatan Pamenang, Merangin, Jambi. Bentuk rumah nyaris sama, setengah kayu, setengah dinding, bagian bawah pakai tembok dan atas pakai kayu. Menuju ke kampung ini, kami melewati hamparan kebun sawit yang mendominasi samping kiri-kanan jalan. Ketika hutan yang jadi ruang hidup Orang Rimba di Jambi, tergerus, pemerintah berupaya bangunkan pemukiman.
Para perempuan Rimba menemui kami sebuah balai kayu di ujung deretan rumah mereka, beberapa sambil menggendong anak.
Penarak, perempuan Rimba cerita, rumah atau sudung mereka dulu di daerah yang ada sumber air dan pangan seperti buah-buahkan atau umbi-umbian. Bila sumber makanan sudah tak ada, mereka pindah lokasi, atau kalau salah satu keluarga mereka sakit sangat keras, mereka pergi (melangun).
Tradisi melangun perlahan hampir hilang seiring hutan yang jadi tempat tinggal mereka tergerus.
Seiring sumber kehidupan hilang, kala hutan lebat beralihfungsi menjadi kebun sawit. Mereka terpaksa mencari berondolan sawit dalam kebun-kebun sawit.
“Ini kan hutan sudah habis, sawit semua, akhirnya cari berondol, lah. Hutan sudah habis,” kata Penarak Juli lalu.
Hasil dari berondol sawit, mereka belikan beras. Dari mengumpulkan butiran-butiran sawit ini hanya cukup untuk makan sehari pula. Mereka sekeluarga mencari sawit bersama-sama. Harga sawit berondolan berkisar Rp3.000 perkg, harga selalu berubah.
“Pokoknya paling satu sak sehari, ada 15 kg,” kata Penarak.
Terkadang, pemilik kebun sawit melarang mereka mengambil buah sawit jatuh karena akan pemilik kebun ambil. Bagi Penarak, itu hal biasa.
Kini mereka pun mengonsumsi beras setelah sumber pangan dari alam tak lagi tersedia. Dulu, makan banar atau gadung (jenis umbi-umbian) yang mereka dapatkan dari hutan.

Segala sirna
Orang Rimba juga menggunakan tumbuhan-tumbuhan di sekitar mereka untuk pengobatan. Sayangnya, tumbuhan obat-obatan itu sudah jarang ditemui, kalau pun ditemui sangat jauh dari tempat mereka tinggal, dimana hutan masih tersisa.
Perlahan, pengetahuan mereka terhadap obat-obatan dari alam memudar. Sebagian mereka masih mengetahui tentang tumbuhan-tumbuhan obat, sebagian tidak.
“Kalau ramuan-ramuannya (masih) tahu, kalau jampi-jampiannya tidak tahu,” kata Suparni, perempuan Rimba, seraya contohkan obat dari daun sengkubung.
Mereka pun kini tidak tahu lagi membuat sandang dari kulit kayu ipuh. Mereka sekadar tahu nenek moyang mereka dulu memakai baju dari kulit kayu ipuh yang dipukul-pukul sampai pipih itu.
Kini, mereka berobat ke fasilitas kesehatan. Bila ada Posyandu, petugas yang mendatangi komunitas langsung, dengan saling berkoordinasi dengan tumenggung (ketua adat).
Yudi, Tumenggung Komunitas Orang Rimba di Pelakar Jaya, sedih memikirkan nasib anak-anak mereka yang tidak mempunyai ruang hidup, mata pencaharian yang bergantung pada berondol sawit, dan dianggap beban pemerintah atau masyarakat lain.
Keterbatasan ruang hidup itu pulalah, kata Yudi, yang menjadi salah satu penyebab kriminalitas di kalangan mereka karena berebut sumber penghidupan, berondolan sawit.
“Masalahnya apa? Masalahnya memperjuangkan isi perut anak-anak ini tadi. Nah, itu yang kita pikir. Padahal cuma permasalahan berondolan,” katanya.

Dia bilang, masih belum terlambat bisa mengatasi itu semua seandainya pemerintah dan perusahaan-perusahaan sawit punya kemauan. Orang Rimba hanya ingin tanah mereka. Mereka lebih dulu hidup dan menjaga hutan di sana dibandingkan para transmigran.
Dulu, mereka tidak tahu tentang administrasi pertanahan atau perhutanan. Yang baru datang, mengambil kesempatan dari ketidaktahuan mereka tentang administrasi atau surat menyurat.
“Kekuatan mereka itu, makanya dibuatkanlah surat zaman sekarang ini. Dulu enggak ada surat, cuma berbatas-batas kayu yang besar, , itu batasnya, ini batasnya.”
Yudi merasa aneh, mengapa Orang Rimba tidak mendapatkan hak atas tanah sedangkan perusahaan dapat hak guna usaha.
Bila ada perusahaan ingin merambah hutan, tempat hidup Orang Rimba, mestinya pemerintah dan perusahaan libatkan mereka.
Belum lagi, akses Orang Rimba untuk memanfaatkan hutan tersisa terbatas. Orang Rimba perlu tanah, tak bisa hidup hanya berdasarkan bantuan beberapa kilogram beras dalam satu bulan dari perusahaan atau pemerintah.
“Itu orang yang kaya. Ibaratnya, kita ini cuman berlindung-lindung di samping-samping. Padahal dia bukan orang sini, orang dari luar, kan itu.”
Ayep, Kepala Desa Pelakar Jaya, bilang, Orang Rimba di Desa Pelakar Jaya ada 33 keluarga dengan 137 jiwa. Di bawah pimpinan Tumenggung Yudi ada 20 keluarga.
Lahan yang Orang Rimba tempati saat ini hibah desa seluas 1,5 hektar, 0,5 hektar untuk pemukiman, selebihnya tanah pertanian.
Orang Rimba sempat tanam sayur-sayuran, tetapi tidak ada yang mau beli hasil tani mereka karena ada stigma buruk terhadap Orang Rimba.
Ayep sadar, apa yang bisa pemerintah lakukan masih terbatas, lahan hanya cukup untuk satu generasi dalam kelompok ini.
“Sekarang ini memang itulah yang jadi beban pikiran kami untuk ke depan. Mereka makin lama jumlah jiwanya makin banyak, kan. Sementara tanah yang ada cuma ini.”
“Cuma kan ya bersyukurnya di antara-antara kelompok yang ini, ada berapa orang yang punya kebun.”
Yudi punya kebun sawit dua hektar dan beberapa sapi. Juga beberapa orang dari komunitasnya ada yang punya sapi. Yang tidak punya kebun atau ternak, menggantungkan hidup pada berondolan sawit.

Serius lindungi
Eko Cahyono, peneliti agraria dan sosiologi perdesaan di Sajogyo Institut, mengatakan, peralihan masyarakat pemburu-peramu menjadi masyarakat agraris yang menetap setidaknya 200-250 tahun.
Perubahan drastis strategi bertahan hidup suatu masyarakat bukanlah hal mudah karena mereka terbiasa mengambil kebutuhan dari alam, dan mengandalkan alam apa adanya.
Sisi lain, pemerintah tidak sepenuhnya mengakui entitas dan eksistensi masyarakat adat. Meski ada pengakuan terhadap hutan adat, tetapi itu tidak menyeluruh. Hutan masyarakat adat masih dianggap wilayah kosong hingga dengan mudah pemerintah memberikan izin terhadap perusahaan pengeksploitasi hutan.
“Mengalifungsikan, atas nama itu adalah hutan produksi, hutan negara, dan semacamnya.”
Apa yang Orang Rimba alami di Jambi seperti stigmatisasi, marginalisasi, eksklusi, dan gizi buruk, juga masyarakat adat alami di daerah lain.
“Kalau tidak ada perubahan mendasar dalam konteks penghormatan sungguh-sungguh pada masyarakat adat, bisa terjadi yang disebut dengan etnogenosida,” kata Eko. 1 Agustus lalu.
Dia bilang, lawan Orang Rimba di Jambi adalah rezim sawit dan taman nasional.
“Ketika hutan hilang karena sawit, mereka enggak lagi punya sumber protein tinggi untuk kehidupan mereka … Sisi lain ketika mereka mau masuk ke wilayah taman nasional, dianggap perambah hutan.”
Kebun sawit yang monokultur menghilangkan biodiversitas, bersamaan dengan alih fungsi hutan, berbagai sumber kehidupan yang biasa masyarakat akses hilang.
“Sumber protein atau sumber gizi masyarakat adat yang biasa bergantung kepada hutan juga hilang. Dampaknya, malnutrisi dan berbagai penyakit merebak di antara mereka.”
Meski pemerintah hadir dengan memberikan bantuan atau akses bagi mereka ke puskesmas atau rumah sakit, katanya, tidak sepenuhnya mengatasi masalah mendasar.
Ada obat seperti apapun, kalau sumber gizi, protein, dan karbohidrat mereka habis, penyakit akan terus merajarela.
Kehidupan masyarakat adat menjadi runtuh karena fondasi dari sistem kehidupan mereka runtuh.
Dia bilang, transisi perubahan sistem kehidupan ini perlu pendampingan pemerintah. Eko menyarankan, jika pemerintah benar-benar ingin mendampingi masyarakat adat, maka basis mata pencaharian harus berbasis tanah. Bukan langsung menjadi pedagang atau peternak agar tidak terjadi gegar budaya.
Masyarakat adat, katanya, perlu kebijakan khusus, butuh affirmative action, tidak bisa sama dengan yang lain.
“Jika transisi itu enggak berhasil, ya sulit dia akan naik kelas lagi,” tegas Eko.
Satu hal penting lagi bagi mereka, kata Eko, mengembalikan citra sebagaimana mestinya, tidak kena stigma. Sebutan-sebutan sinis atau stigmatik terhadap masyarakat adat harus kikis
Menurut Eko, pandangan-pandangan stigmatik itu punya implikasi yang serius dalam kehidupan mereka.
“Karena mereka punya tradisi yang lama, budaya yang lama, nilai-nilai adat yang lama, yang itu juga sulit otomatis langsung ditinggalkan.”

*****
Nasib Orang Rimba di Tengah Himpitan Perkebunan Sawit dan Tambang Batubara