- Masyarakat adat Dayak Meratus, merasa terancam atas rencana penetapan Taman Nasional (TN) Meratus. Mereka khawatir kehilangan tanah warisan leluhur karena adanya pembatasan aktivitas dalam zona yang dapat memusnahkan identitas komunitas lokal.
- Para ahli menilai konsep taman nasional yang mengacu pada model asing tidak cocok diterapkan di Pegunungan Meratus. Konservasi berbasis kearifan lokal telah lama dijalankan masyarakat adat melalui praktik seperti hutan keramat dan tabu lingkungan, tanpa perlu intervensi negara.
- Pengalaman dari taman nasional lain di Indonesia menunjukkan kegagalan perlindungan lingkungan dan kerugian masyarakat adat. Sejumlah TN justru dipenuhi aktivitas tambang dan sawit, ditambah akses informasi yang terbatas, sehingga memunculkan keraguan terhadap efektivitas TN itu sendiri.
- Peta wacana TN Meratus memperlihatkan tumpang tindih dengan wilayah adat, balai dan izin tambang aktif. Ironisnya, banyak komunitas adat belum diakui secara hukum, padahal kawasan yang akan ditetapkan sebagai taman nasional justru merupakan ruang hidup dan penghidupan utama mereka.
Pinan, Masyarakat Adat Dayak Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, tak bisa menyembunyikan kekhawatiran rencana penetapan Taman Nasional (TN) Meratus. Dia takut kampung halamannya, Desa Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masuk dalam area usulan.
Apalagi kalau masuk zona inti, bakal membatasi akses dan aktivitas manusia. Warga bisa kehilangan tanah warisan leluhur. Ujung-ujungnya, mereka akan punah.
“Daripada tersingkir, kami memilih mempertahankan tanah ini dengan jiwa raga,” katanya.
Rudy Redhani, Livelihood Specialist Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, memandang wajar keresahan Pinan. Sebab, dalam setiap tanam nasional, akan ada kriteria pembagian zona yang termaktub dalam sejumlah regulasi.
Misal, Undang-undang Nomor 5/1990, Peraturan Pemerintah Nomor 28 2011, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 76/2015. Kawasan inti merupakan zona yang paling terlindung. Tak boleh ada kegiatan, kecuali untuk kepentingan penelitian, pendidikan, atau ilmu pengetahuan, itu pun dengan izin khusus.
Selanjutnya, ada zona rimba, penyangga zona inti. Keaslian pada kawasan ini harus terjaga, terbatas untuk konservasi ekosistem dan habitat satwa.
Ada juga zona pemanfaatan, seperti untuk wisata alam, penelitian, pendidikan, serta jasa lingkungan. Seluruh aktivitas di zona ini harus tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak keseimbangan ekosistem.
Kemudian, zona tradisional atau zona lainnya sesuai keperluan. Hanya masyarakat lokal yang boleh beraktivitas. Misal, pengambilan hasil hutan non-kayu sepanjang tetap lestari dan tidak merusak lingkungan.
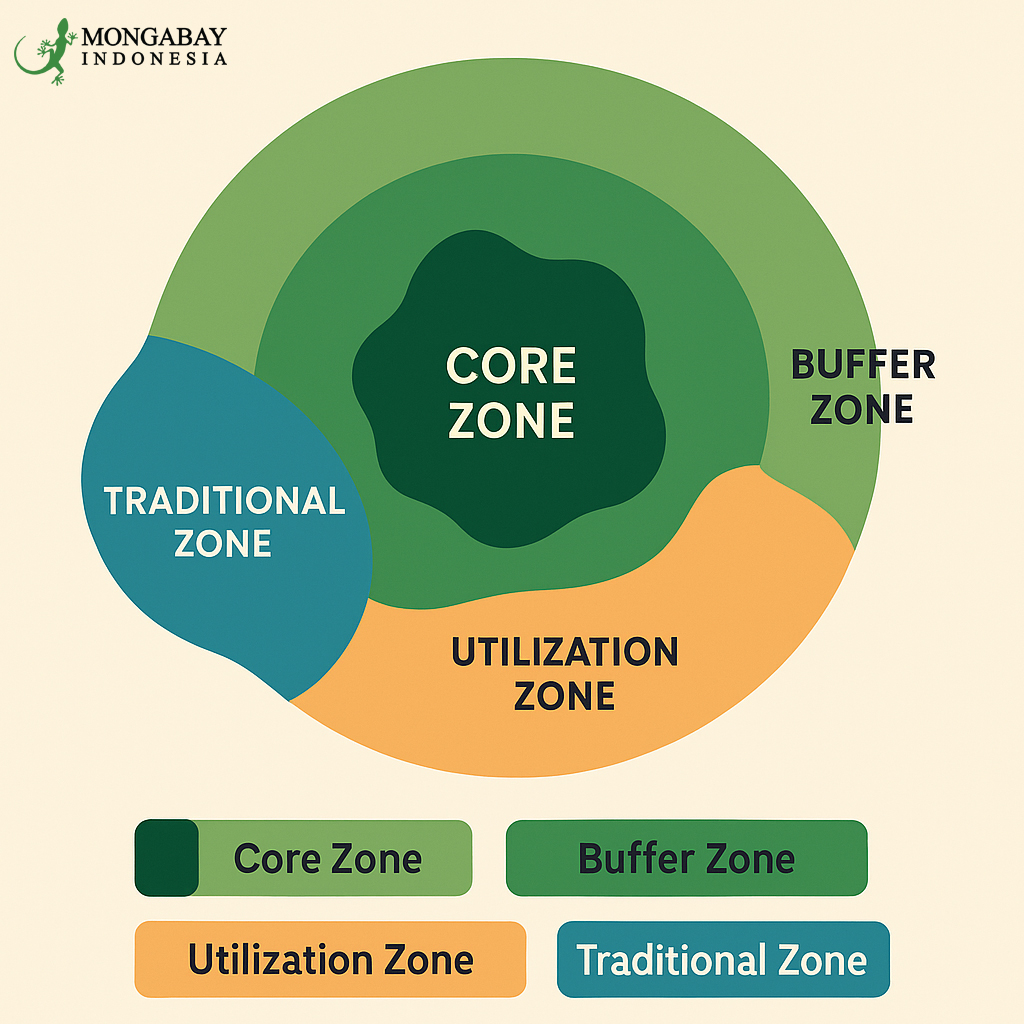
Udur, sapaan akrabnya, bilang, fungsi taman nasional bukanlah konsep yang tepat untuk Masyarakat Adat Dayak di Pegunungan Meratus. Yang lebih tepat ialah perpaduan konservasi konvensional berbasis akademik dengan konservasi berbasis tradisi.
“Dasar hukum pun seharusnya disusun berdasarkan konteks lokal, bukan mengadopsi secara mentah konsep national park yang berasal dari lembah Yosemite di Amerika Serikat yang jelas berbeda baik dari segi sosial, budaya, maupun ekologi dengan wilayah seperti Kalimantan,” katanya.
Achmad Rafieq, Ketua Asosiasi Antropolog Indonesia (AAI), menyebut, apabila alasan pembentukan fungsi taman nasional hanya berdasarkan hutan konservasi, maka masyarakat di Pegunungan Meratus sejatinya sudah lebih dulu mempraktikkannya.
Masyarakat adat pun menolak aktivitas yang merusak lingkungan, seperti pertambangan dan pembalakan liar lewat hutan keramat.
Mereka, katanya, memiliki pengetahuan adat (indigenous knowledge) seperti istilah pantangan (tabu) yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologi.
“Melalui kearifan lokal, mereka menjaga kelestarian alam secara turun-temurun, jauh sebelum negara mengenal konsep tersebut,” kata Dosen Antropologi Universitas Lambung Mangkurat itu.
Praktik masyarakat adat melalui hutan keramat ini terbukti lewat analisis data Global Forest Watch. Dari 2002-2024, area di sekitar peta wacana TN Meratus hanya kehilangan tutupan pohon 1,9% dari total 2000.
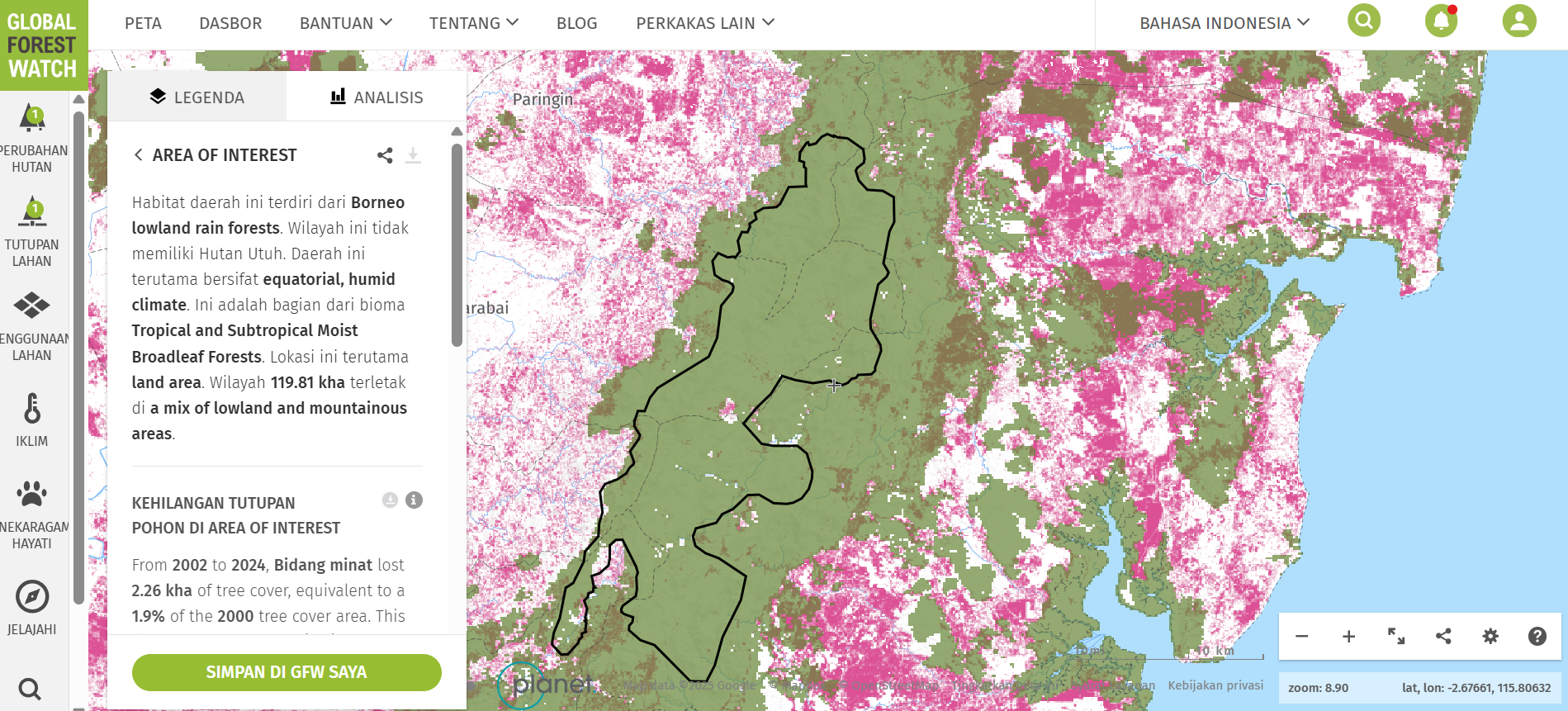
Belajar dari taman nasional lain
Basuki Budi Santoso, Staf Restorasi Friends of Nature, People, and Forest, menyebut, pemerintah harusnya belajar dari pengalaman di tempat lain sebelum menetapkan status TN Meratus. Masyarakat, katanya, banyak merugi karena keputusan ini.
Pengalamannya selama dua dekade mendampingi kawasan taman nasional di berbagai daerah membuatnya prihatin nasib masyarakat adat. Dia khawatir, kondisi serupa terjadi di Pegunungan Meratus.
“Taman nasional itu tidak semerdu apa yang kita dengar sebenarnya,” katanya dalam diskusi bertema Meratus di Persimpangan Jalan helatan Komunitas Gemar Belajar Banjarmasin dan Equal, berkolaborasi dengan Mongabay.
Di Taman Nasional Tanjung Puting, misal, Desa Sungai Cabang, Teluk Pulih, dan Sungai Perluh dulu berada dalam taman nasional. Belakangan, desa-desa itu pemerintah keluarkan dari zona konservasi, membuka jalan masuknya izin perusahaan sawit.
Pemerintah pun tidak bisa menahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah itu hingga 25%. Belum lagi, ada kegiatan ilegal seperti pertambangan emas dan perkebunan sawit. Sedang, akses informasi sangat tertutup.
“Saking ketatnya aturan, tak sembarang orang bisa masuk dan mengekspos kondisi di dalam kawasan. Butuh izin yang sulit, dan banyak informasi akhirnya tidak pernah muncul ke permukaan.”
Serupa dengan Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur, habitat banteng kini rusak parah. Kawasan ini justru penuh tambang batubara. Meski memiliki anggaran Rp15 miliar per tahun pada 2021, kawasan itu tetap saja hancur.
Pria berambut gondrong ini mempertanyakan konsep wacana TN Meratus ke depan. Karena, 57 taman nasional yang ada, lebih 16 juta hektar saja tidak mampu pemerintah kelola dengan baik.
Wacana ini akan menambah masalah baru. Apalagi ada masyarakat adat yang menghuni Pegunungan Meratus.
“Sekarang, saya tidak melihat ada urgensinya.”
Bukan tanah kosong
Data yang Mongabay terima dari pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat sipil menunjukkan rencana TN Meratus mencakup area 119.779 hektar. Di dalamnya, ada puluhan desa di sembilan kecamatan dan 5 Kabupaten yang saling terhubung.
Data penduduk periode akhir 2024 yang Mongabay himpun di setiap kecamatan dan Disdukcapil per kabupaten menunjukkan ada sekitar 20.328 jiwa yang terdiri dari 6.032 keluarga. Mereka terancam kehilangan tempat tinggal karena wacana TN Meratus.
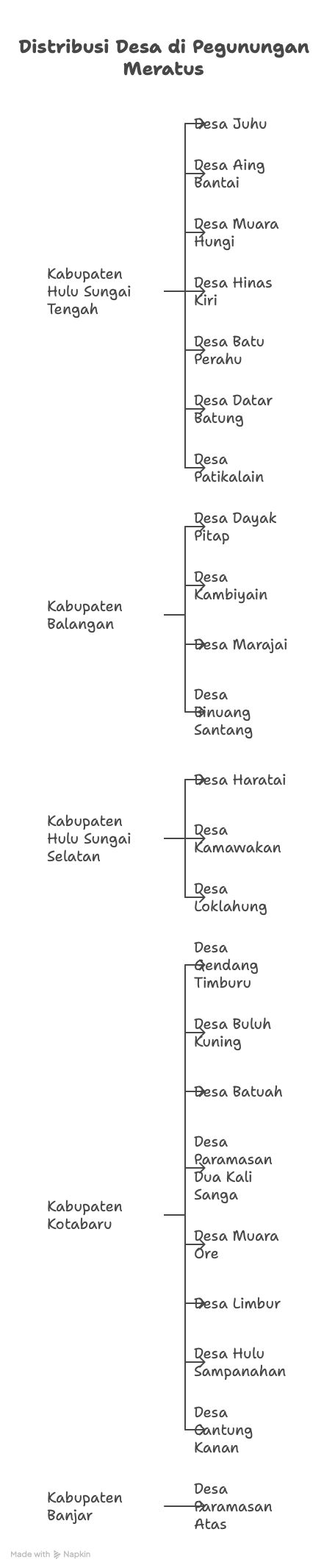
Analisis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan, juga menunjukkan sebagian besar area yang rencananya jadi TN Meratus merupakan wilayah hunian komunitas adat dan lokasi usaha masyarakat.
Saat ini, terdapat 146 komunitas adat yang terdata di Kalimantan Selatan, dan jumlah ini akan terus bertambah. Dalam peta wacana taman nasional, banyak wilayah saling bersinggungan dan tumpang tindih dengan sebaran balai adat.
Di Kabupaten Kotabaru, misal, ada Balai adat Batuah, Maantam, Kita, Gendam Timburu, Muara Orie, Banian, Buluh Kuning, Maramis, Gawu, Suliyan, Limbur, Maisi, Malangkayan, dan Hulu Sampanahan.
Di Kabupaten Banjar, kawasan berpotensi terdampak mencakup Balai Adat Paramasan Bawah (Balai Induk), Paramasan Atas, Babangin, dan Mangapan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), komunitas adat yang tinggal di Balai Sungai Binti, Uling-Uling, Malaris, Manakili, Makunting, Loa Panggang, Janggar, dan Kedanyang juga masuk dalam rencanataman nasional.
Lalu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mencakup Balai Kiyo, Datar Tarap, Pasumpitan, Ramang, Mula Ada, Kapal, Haraan Jumbuk, Buhul, Batu Perahu, Manggajaaya, Datar Batung, Mindai, dan Pata.
Di Kabupaten Balangan, ada balai adat Ajung, Tayan, Sangkar Manyurung, Sain, Kambiyain, Dewa Putir, Lancuran Mayang, Wadah, Kurihai, Tanjung Jailamo, dan Andamai.
Rubi, Ketua AMAN Kalsel, berkata, pengakuan terhadap masyarakat adat justru tertinggal kala negara bergegas menetapkan Meratus sebagai taman nasional. Sebab, hanya dua dari lima kabupaten yang memiliki regulasi formal.
Sementara, Kabupaten Kotabaru memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). Sayangnya, belum satupun komunitas adat yang mendapatkan pengakuan resmi.
“Peraturannya memang sudah terbit, tapi belum ada satupun komunitas adat yang diakui.”
Kemudian ada Kabupaten HSS yang juga mengantongi Perda Nomor 1/2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.
Hanya ada empat komunitas (belum termasuk hak atas hutan adat) yang pemerintah daerah akui. Yakni, Kerukunan Balai Adat Datu Kandangan di Desa Ulang yang menaungi sembilan balai adat Dayak Meratus, yaitu Mawak, Wariung, Datar Buluh, Kacang Parang, Madamang, Jualian, Bangka-un, Batu Balah, dan Hambawang Masam. Total wilayah adat yang mereka kelola mencapai 2.712,32 hektar.
Lalu Karukunan Balai Adat Datung Makar di Desa Malinau yang mencakup tiga balai, Jalai, Bidukun, dan Padang, dengan wilayah seluas 4.386,78 hektar.
Kemudian, Karukunan Balai Adat Bayumbung di Desa Halunuk mengelola 769,20 hektar. Serta Karukunan Keturunan Datu Mayawin-Urui di Desa Loksado memiliki wilayah adat seluas 1.603,36 hektar.
Sementara, masyarakat adat di desa-desa yang masuk ke dalam rencana TN Meratus masih belum mendapatkan pengakuan. Tiga kabupaten lainnya bahkan masih tertatih-tatih menyusun aturan. Kabupaten Balangan, sudah mulai membahas rancangan perda sejak 2023, namun hingga kini masih jalan di tempat.
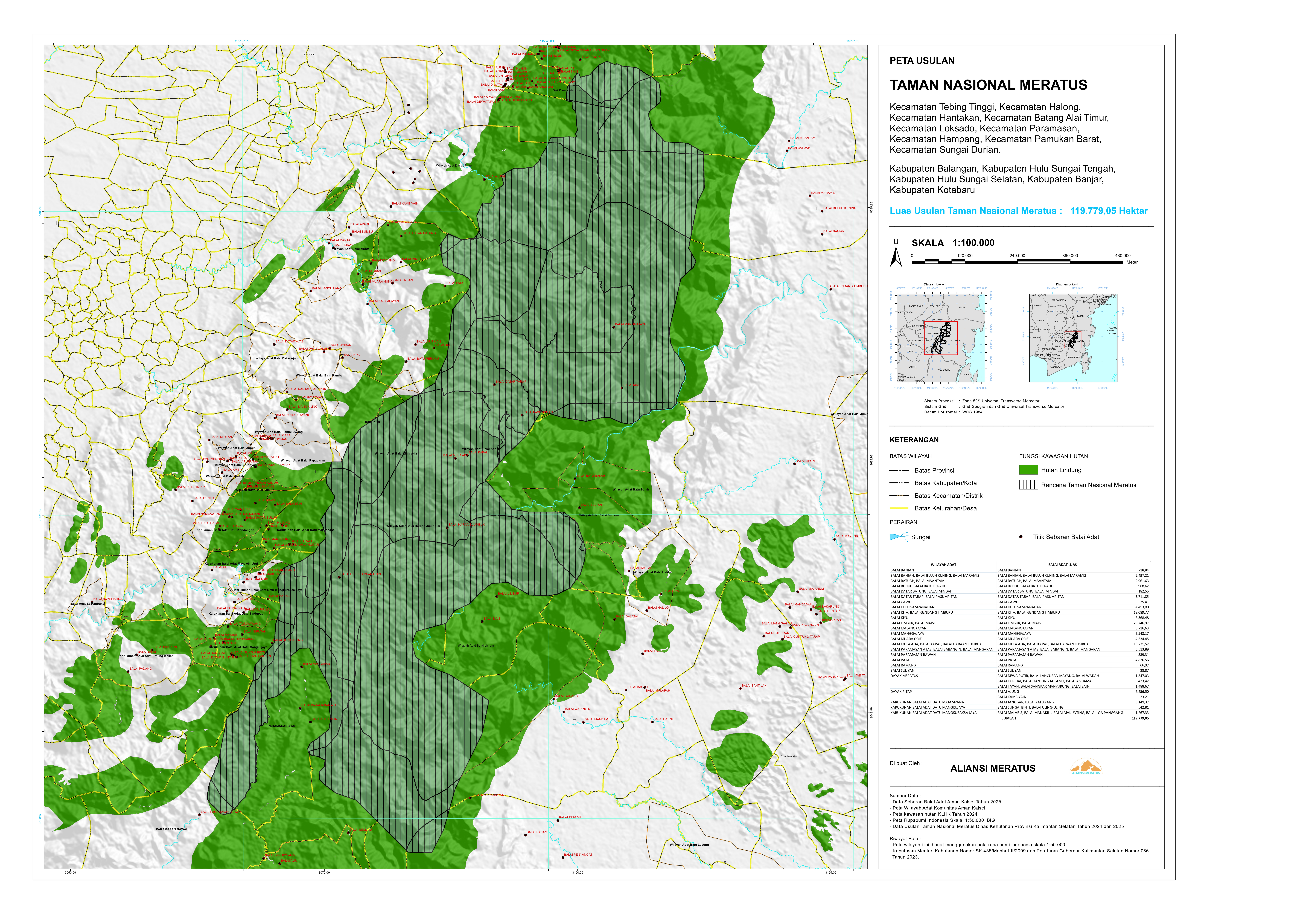
Tidak partisipatif
Hingga saat ini, sebanyak 30 organisasi telah menyatakan penolakan keras terhadap rencana tersebut karena berisiko mengusir serta hilangnya akses masyarakat terhadap pangan, obat-obatan, dan ritual adat. Pemerintah juga tidak melibatkan dan berdiskusi dengan masyarakat ihwal rencana ini.
Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, menyebut, proses pengusulan taman nasional tidak transparan.
“Hal ini terbukti dari masih banyaknya komunitas adat yang tidak mengetahui wilayah mereka masuk dalam perencanaan kawasan taman nasional.”
Seingatnya, pemerintah juga dulu tiba-tiba mendapuk kawasan Pegunungan Meratus sebagai hutan lindung. Padahal, kawasan tersebut sejak lama berpenghuni.
Penetapan itu pun minim melibatkan masyarakat. Akibatnya, sampai sekarang masih banyak yang belum mengetahui status ini.
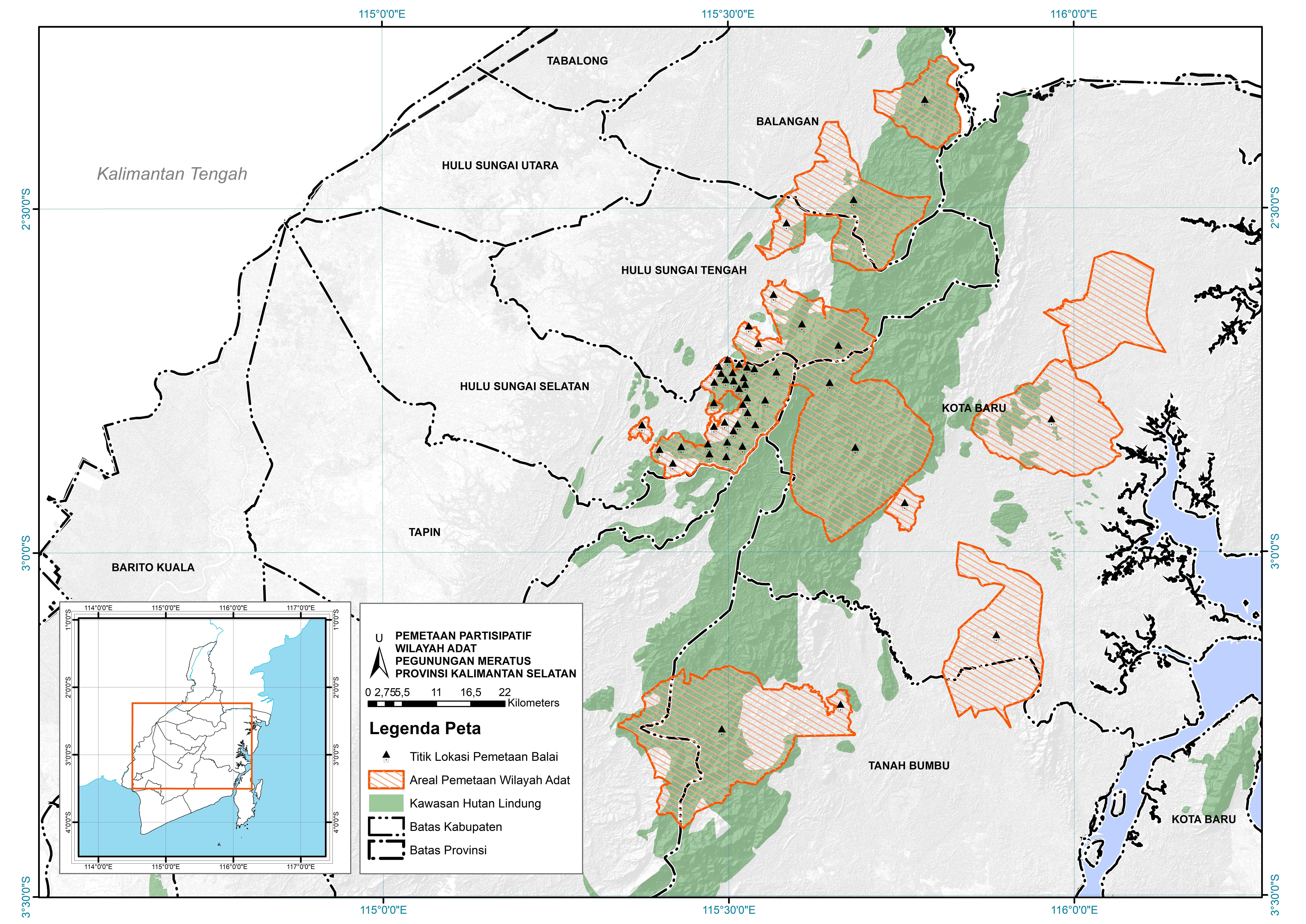
Bak jatuh tertimpa tangga, masyarakat di Pegunungan Meratus kini juga tidak sadar puluhan perizinan dari berbagai sektor mengepung mereka, mulai dari sawit hingga tambang. Dari total luas Kalsel yang mencapai sekitar 3,7 juta hektar, izin usaha telah membebani sekitar 51% wilayah, termasuk kawasan hutan lindung.
Kawasan Pegunungan Meratus yang membentang seluas kurang lebih 504.333 hektar tercatat memiliki 165 izin usaha pertambangan aktif.
“Tambang dan perkebunan sawit telah menggerus lebih dari 300.000 hektar tutupan lahan sejak 1990-an.”
Konsesi pertambangan paling mencolok terlihat di bagian utara Kabupaten Kotabaru. Peta wacana taman nasional pun terlihat tumpang tindih dengan konsesi pertambangan emas PT Pelsart Tambang Kencana, perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang beroperasi dengan sistem tambang bawah tanah (underground).
Konsesi itu berada di sekitar Damardatar, masuk hutan lindung. Temuan ini memicu kekhawatiran risiko konflik kepentingan antara pelestarian lingkungan dan aktivitas ekstraktif.
Septamto L Inkriwang, Manajer CSR PT Pelsart Tambang Kencana belum dapat memberikan tanggapan terkait masuknya sebagian wilayah konsesi perusahaan tempat dia bekerja di dalam wilayah yang akan menjadi taman nasional.
“Belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah sehingga kami belum bisa memberikan pernyataan,” katanya membalas pesan singkat Mongabay.
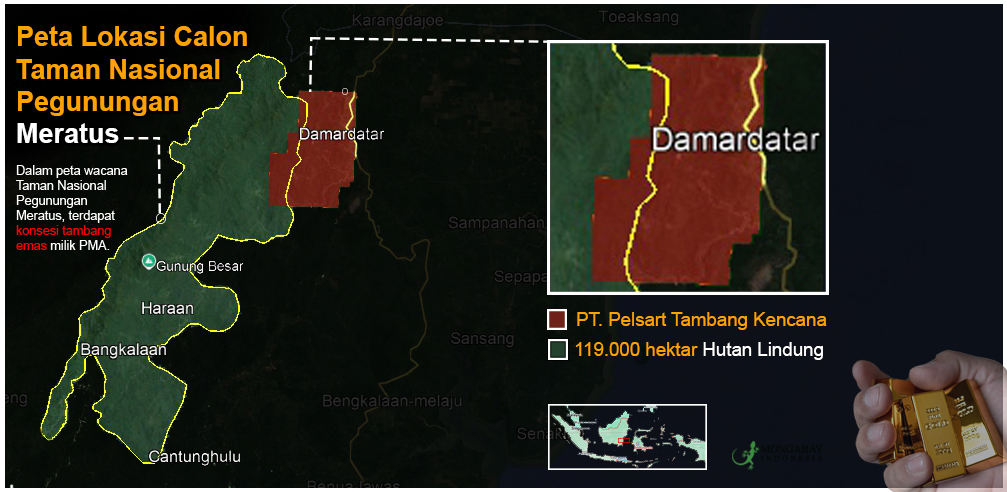
Beni Raharjo, Kepala Bidang Planologi dan Pengelolaan Hutan Dishut Kalsel, angkat bicara. Dia bilang, perusahaan itu masuk daftar 13 pengecualian aktivitas dalam kawasan hutan lindung.
Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41/2004 soal perizinan atau perjanjian bidang pertambangan di kawasan hutan.juga payung hukum lain, termasuk sejumlah UU dan peraturan pemerintah.
Kebijakan pengecualian, katanya, merupakan respons terhadap perjanjian kontrak karya yang ada sebelum UU Kehutanan (UU No. 41/1999) yang secara umum melarang penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.
“Saat zaman ibu Megawati, Pelsart ini dikecualikan. Tetapi ada kemungkinan nanti tetap akan dikeluarkan dari taman nasional, itu dipotong.”
Soal perkembangan wacana TN Meratus, dia bilang sudah melalui sebagian dari 10 tahapan tentatif. Seperti penyusunan data dan informasi umum, naskah akademik hingga informasi detail, rapat kajian kebijakan pengelolaan Pegunungan Meratus, sampai permohonan perubahan fungsi oleh gubernur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, September hingga Oktober 2024.
Hingga pertengahan Juli 2025, mereka masih menunggu pembentukan tim terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Jadwal ini, katanya, agak molor dari tenggat, karena masih terkendala anggaran.
Setelah tahapan itu selesai, tim akan melakukan penelitian lapangan sebelum keputusan menteri rencananya keluar paling lambat Desember 2025. “Saat ini kita masih menunggu.”
Dia juga berjanji dan memastikan penetapan taman nasional di Pegunungan Meratus tidak akan mengganggu kearifan lokal sampai komunitas di dalamnya. Sebab, akan ada penyusutan luas area dari rencana awal 199.000 hektar karena revisi.
“Menurut saya itu (penyingkiran masyarakat adat) tidak akan terjadi lah, karena pegunungan Meratus itukan intensitas kita yang melekat ke Dayak Meratus, kita akan mengakomodir itu.”
Begitu pula dengan luasan peta kawasan sementara, tidak harus utuh dalam satu hamparan, melainkan bisa tersebar dan terbagi di beberapa titik untuk menghindari wilayah masyarakat adat.
“Pembagian zonasinya kapan? Memang belum sekarang, kita juga melihat ada kampung di tengah seperti Desa Juhu itu.”
Penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional, katanya, memiliki sejumlah manfaat strategis, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, berpotensi meningkatkan citra dan peran daerah, mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta membantu pengendalian bencana alam.
Selain itu, taman nasional juga bisa mengoptimalkan pembangunan sektor kehutanan dan membuka peluang kolaborasi internasional.
Bagi masyarakat, kata Beni, keberadaan taman nasional dapat memberikan dampak positif peningkatan ekonomi, pemberdayaan melalui bantuan dan kerjasama, pelestarian budaya lokal, hingga pemanfaatan kawasan taman nasional secara langsung.

*****













