- Sawit Watch bersama tim kuasa hukum mengajukan permohonan uji materiil dan tafsir ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah pasal dalam UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, akhir tahun lalu. Mereka menilai, beberapa pasal terutama setelah berubah lewat UU Nomor 6/2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja ini rentan bagi masyarakat adat dan petani kecil. Sidang uji materi telah bergulir sejak akhir 2024 kini memasuki tahap akhir.
- Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, dalam diskusi daring 24 Juli lalu. berharap, putusan Mahkamah Konstitusi bisa jadi penentu arah masa depan petani kecil dan masyarakat adat dalam lanskap hukum kehutanan dan perkebunan di Indonesia.
- Grahat Nagara, dosen Hukum Agraria di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Senior Associate di Woods & Wayside Internasional ini khawatir pasal-pasal itu jadi alat represif terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di kawasan hutan.Masyarakat sekitar kawasan hutan kena tuduhan ilegalitas, padahal banyak yang turun-temurun hidup dan menggantungkan mata pencaharian di sana.
- Gunawan, Penasihat Senior Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), menyampaikan pandangan terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU P3H, terutama setelah perubahan melalui UU Cipta Kerja. Perubahan regulasi itu memperluas ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini tinggal dan bercocok tanam di dalam kawasan hutan.
Sawit Watch bersama tim kuasa hukum mengajukan permohonan uji materiil dan tafsir ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah pasal dalam UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, akhir tahun lalu. Mereka menilai, beberapa pasal terutama setelah berubah lewat UU Nomor 6/2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja ini rentan bagi masyarakat adat dan petani kecil. Sidang uji materi telah bergulir sejak akhir 2024 kini memasuki tahap akhir.
“Pemerintah harus memberikan kepastian dan keadilan hukum, serta bersikap persuasif terhadap masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan. Khusus, mereka yang belum tercakup dalam kebijakan penataan kawasan hutan,” kata Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, dalam diskusi daring 24 Juli lalu.
Dia berharap, putusan Mahkamah Konstitusi bisa jadi penentu arah masa depan petani kecil dan masyarakat adat dalam lanskap hukum kehutanan dan perkebunan di Indonesia.
Sawit Watch menggugat Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B. Pasal-pasal ini mereka anggap tak berpihak pada kelompok masyarakat rentan, terutama masyarakat adat dan pekebun sawit kecil di lahan yang negara klaim di dalam kawasan hutan.
Dalam permohonannya, Sawit Watch menyampaikan, keberadaan dan penerapan pasal-pasal itu justru menghalangi upaya menuju transformasi sektor sawit lebih berkelanjutan, terutama sawit bebas deforestasi.
Rambo mengatakan, langkah ini mereka ambil sebagai upaya mendorong kepastian, keadilan hukum, serta perlindungan lebih kuat bagi petani kecil dan masyarakat adat di dalam kawasan hutan.
Di banyak wilayah, katanya, konflik antara masyarakat dan negara terkait klaim kawasan hutan terus berlangsung. Satu contoh, katanya, terjadi di Desa Ujung Gading Julu, Kecamatan Simangambat, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
“Masyarakat di sana mencoba mendaftarkan tanah yang mereka kelola turun-temurun ke Badan Pertanahan Nasional, namun permohonan itu ditolak dengan alasan lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan,” kata Rambo, dalam diskusi 24 Juli lalu.
Situasi ini, katanya, mencerminkan problem klasik, yakni, tumpang tindih klaim antara tanah adat, hak kelola rakyat, dan status kawasan hutan yang tak pernah benar-benar tuntas sejak Orde Baru.
Bagi petani dan pekebun kecil, kejelasan hukum atas tanah adalah segalanya. “Tanpa itu, mereka berada dalam posisi rawan, bisa digusur kapan saja, atau lebih buruk lagi, dikriminalisasi.”
Dia contohkan kondisi teranyar di Riau, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tengah menertibkan kebun sawit di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Aksi ini jadi sorotan karena menimbulkan reaksi pro dan kontra. Satu sisi, penegakan hukum penting untuk menjaga kawasan konservasi yang rusak oleh ekspansi sawit ilegal.
“Sisi lain, muncul pertanyaan: siapa yang ditertibkan? siapa yang dibiarkan?”
Seringkali, katanya, yang jadi target adalah petani kecil yang tidak memiliki akses informasi, dokumen, atau kekuatan hukum.
Sedangkan pelaku skala besar yang kemungkinan kuat, membuka ribuan hektar dalam kawasan, justru sulit tersentuh hukum. “Karena keterkaitannya dengan modal dan kekuasaan,” katanya.

Ketidakadilan
Jondamay Sinurat, Kuasa Hukum Sawit Watch mengatakan, pasal-pasal yang mereka mohonkan tampak biasa di atas kertas, tetapi di balik itu, tersembunyi ketidakadilan.
Salah satunya, frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan.” Menurut Jondamay, kalimat pendek ini menyisakan luka panjang bagi masyarakat yang lama mendiami dan rawat turun-temurun, bahkan sejak sebelum republik ini berdiri.
“Kami bertanya, bagaimana nasib mereka yang tak sempat atau tak tahu cara mendaftar? Bagaimana masyarakat adat, yang secara historis bagian tak terpisahkan dari ekosistem hutan, harus tunduk pada mekanisme administratif yang bahkan tidak pernah transparan bagi mereka?” katanya.
Apalagi, katanya, mekanisme pendaftaran itu tak jelas. Tak jarang, masyarakat terbebani syarat-syarat administratif yang tidak sesuai realitas sosial mereka.
Ketika tak bisa memenuhi syarat itu, katanya, mereka justru kena kriminalisasi.
“Petani kecil dihukum, perusahaan besar dapat ampun. Inilah wajah ketimpangan yang coba kami lawan dengan langkah hukum.”
Lebih ironis lagi, katanya, di banyak kawasan hutan, negara hadir secara administratif tetapi absen secara substantif.
“Ada sekolah, puskesmas, masjid, bahkan kantor desa. Pemerintah menyelenggarakan pemilu di sana, warga memilih, dan pemimpin dilantik. Ketika masyarakat memperjuangkan hak atas tanahnya, negara tiba-tiba menyebut mereka ‘ilegal’.”
Selain itu, mereka juga menyoroti frasa “kegiatan lain” dalam Pasal 110. Frasa ini multitafsir, membuka ruang bagi aparat penegak hukum menindak masyarakat atas dasar tuduhan kabur.
Masyarakat yang menanam sawit untuk hidup, bisa saja kena tuduh melakukan “kegiatan lain” yang dilarang.
“Ini bukan hanya problem hukum, tapi problem kemanusiaan. Kami tegaskan, sebelum negara ini hadir, masyarakat lebih dulu hidup di sana.”
Mereka, katanya, bukan pelanggar hukum. Mereka adalah pengelola hutan, bagian dari lanskap sosial-ekologis yang mestinya terlindungi, bukan jadi korban demi ekspansi modal.
Untuk itu, mereka mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar menghapus frasa-frasa bermuatan diskriminatif dalam pasal-pasal itu.
Mereka juga meminta, MK memberikan tafsir adil dan kontekstual agar hukum tidak sekadar sebagai teks kaku, melainkan instrumen keadilan yang hidup dan relevan dengan realitas sosial.
“Harapan kami sederhana, hukum tidak boleh hanya melayani mereka yang kuat dan terdaftar. Hukum harus hadir juga untuk mereka yang menjaga tanah ini tanpa pengakuan, petani kecil, masyarakat adat. Semua yang lama hidup berdampingan dengan hutan.”

Rentan jadi alat refresif kepada rakyat kecil
Grahat Nagara, dosen Hukum Agraria di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Senior Associate di Woods & Wayside Internasional ini khawatir pasal-pasal itu jadi alat represif terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di kawasan hutan.
Masyarakat sekitar kawasan hutan kena tuduhan ilegalitas, padahal banyak yang turun-temurun hidup dan menggantungkan mata pencaharian di sana.
“Banyak contoh kasus di lapangan, tinggal bertahun-tahun di kawasan hutan justru dikriminalisasi dan diperlakukan seolah-olah pelaku tindak pidana,” kata akademisi yang berfokus pada kebijakan hukum pidana dan tata kelola agraria ini.
Menurut Grahat, persoalan mendasar terletak pada bagaimana negara memposisikan pasal-pasal ini dalam kerangka hukum dan kebijakan agraria yang lebih luas.
Dia bilang, ada tiga tahapan utama dalam proses yang menyebabkan masyarakat adat dan lokal tereksklusi dari penguasaan tanah mereka.
Pertama, proses formalisasi asimetris, hak-hak masyarakat adat tidak diakui setara oleh negara. Meskipun hukum adat diakui sebagai sumber hukum agraria, dalam praktik tidak ada pengkodifikasian dan pengakuan konkret.
“Ini mengakibatkan hak-hak tradisional masyarakat menjadi tidak terlihat secara legal.”
Kedua, informalisasi dan penyangkalan hak, yaitu ketika hak-hak masyarakat sudah lama terabaikan kemudian secara aktif negara sangkal.
Contohnya, pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kepada korporasi meskipun pengukuhan kawasan hutan belum selesai. Secara tak langsung, katanya, menyangkal hak masyarakat atas tanah itu.
Ketiga, represifitas dan eksklusi, negara menggunakan instrumen hukum pidana untuk pengusiran dan kriminalisasi masyarakat. Proses ini, katanya, seringkali berbarengan dengan tindakan represif yang menyulitkan masyarakat bertahan di kawasan hutan.
“Ini bukan sekadar kriminalisasi biasa, tetapi sebuah pembajakan konsep hak menguasai negara yang seharusnya berfungsi untuk kesejahteraan rakyat, malah jadi alat untuk memproduksi eksklusi hak warga negara,” kata Grahat.
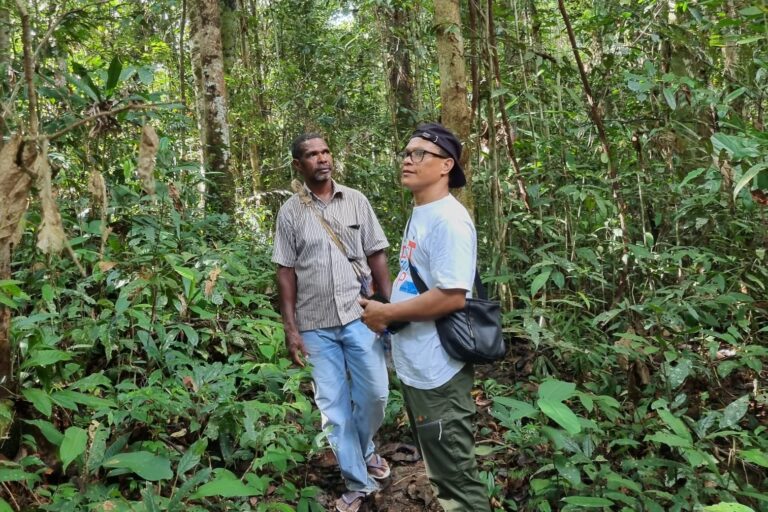
Gunawan, Penasihat Senior Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), menyampaikan pandangan terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU P3H, terutama setelah perubahan melalui UU Cipta Kerja.
Dia menegaskan, perubahan regulasi itu memperluas ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini tinggal dan bercocok tanam di dalam kawasan hutan.
Menurut Gunawan, dalam Pasal 12A, 17A, dan 110B UU P3H berisiko sebagai alat mempidanakan masyarakat yang justru seharusnya masuk pengecualian dari ancaman sanksi.
Pasal-pasal itu, katanya, mengatur larangan menebang pohon, berkebun, dan melakukan “kegiatan lain” di kawasan hutan tanpa izin, dan menetapkan batasan lima tahun, lima hektar, serta syarat “terdaftar” bagi pengecualian sanksi.
“Masalahnya, masyarakat memang dikecualikan, tapi pengecualiannya diberi syarat tambahan yang ketat. Akhirnya, masyarakat tetap rentan dikenakan sanksi karena sulit memenuhi seluruh persyaratan administratif tersebut.”
Dia menyoroti, peraturan sebelumnya seperti Peraturan Presiden tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebenarnya memberikan ruang perlindungan melalui mekanisme reforma agraria.
Namun, regulasi itu telah dicabut dan tergantikan melalui integrasi dalam kebijakan percepatan reforma agraria pasca UU Cipta Kerja.
“Ketika PPTKH dihapus dan mekanisme penyelesaiannya digeser ke ranah administratif baru, muncul kekacauan legal yang memperburuk perlindungan hak masyarakat,” ujar Gunawan.
Persoalan utama dalam regulasi ini, katanya, adalah tercampurnya subjek hukum antara masyarakat yang seharusnya terlindungi dengan pihak-pihak yang layak kena sanksi.
Campur baur ini, katanya, menciptakan dampak serius, baik terhadap kebijakan reforma agraria maupun kepastian hukum secara keseluruhan.
“Ketika subjek yang harusnya dilindungi malah dimasukkan dalam daftar pelanggar, maka itu bukan hanya bentuk kelalaian administratif, tapi juga pelanggaran konstitusional.”
Dia juga menekankan, perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif dalam beberapa kasus tidak menjawab substansi masalah.
“Pemberian sanksi administratif bukan solusi kalau tetap tidak menyelesaikan akar masalah ketidakadilan struktural. Itu juga berdampak pada dinamika hubungan internasional kita, seperti komitmen terhadap ISPO, RSPO, atau isu deforestasi global,” katanya.

*****













