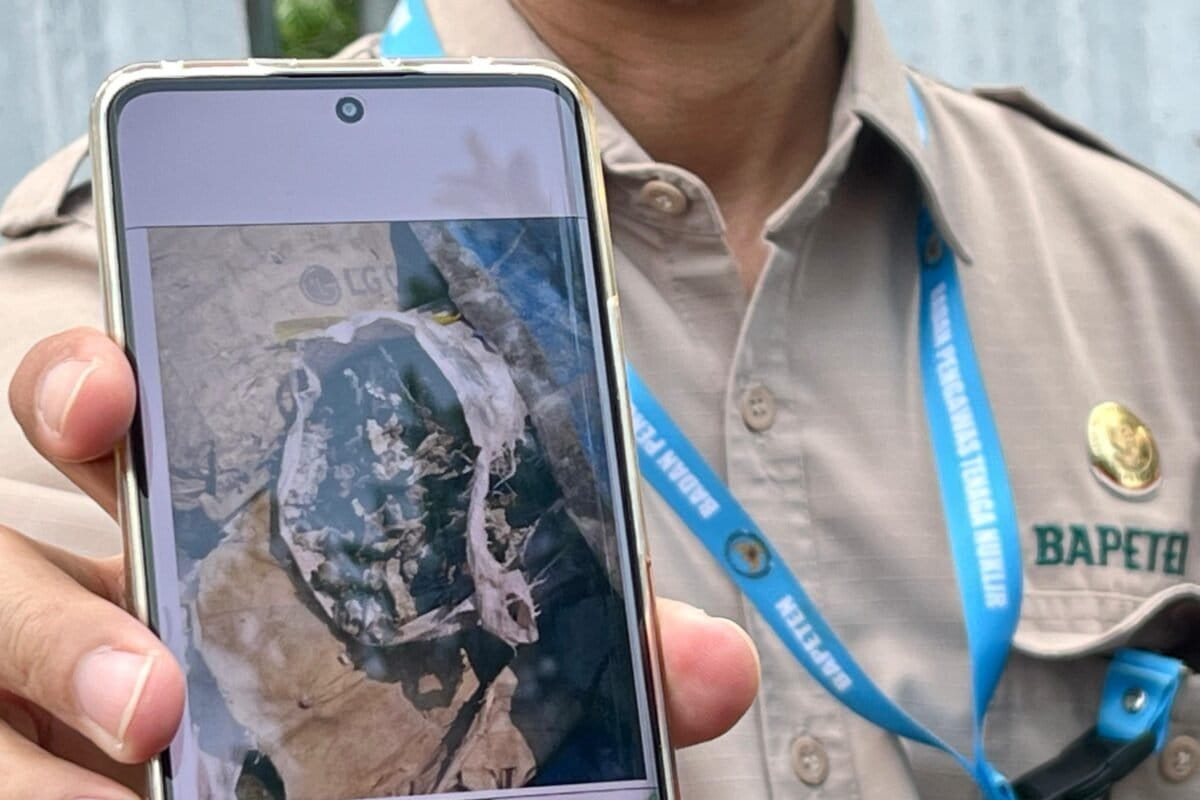- Suku Semende adalah suku yang hidup di sekitar sumber mata air tujuh sungai atau “Tumutan Tujuh”. Ketujuh sungai itu antara lain Sungai Padang Guci, Air Kinal, Air Bengkenang, Air Kendurang di Bengkulu, serta Sungai Lematang, Sungai Enim, dan Sungai Ogan.
- Permukiman tua Suku Semende berada di hulu Sungai Enim, Sungai Ogan dan Sungai Lematang. Tepatnya di hulu Aik Enim Kidaw, Aik Enim Tengah, Endikat, Ogan Kanan dan Ogan Kiri.
- Terhadap sungai dan mata air, Suku Semende memiliki aturan adat. Pertama, dilarang membangun rumah atau permukiman di tepi sungai atau mata air, dilarang menebang pohon di sekitar sungai dan mata air, dan mengambil batu dari sungai.
- Kelangsungan hutan yang terjaga akan mendukung keberlanjutan pasokan air alami yang sangat penting bagi pertanian dan perkebunan di Semende. Proyek panas bumi memiliki kepentingan besar dalam menjaga kelestarian hutan untuk jangka panjang.
Suku Semende yang terbentuk sejak abad ke-17 di wilayah perbukitan Gunung Patah atau bagian timur Bukit Barisan Selatan, Sumatera Selatan, pada ketinggian 1.000-1.500 mdpl, terus bertahan. Ini dikarenakan masih terjaganya sumber mata air tujuh sungai, yang dikenal sebagai “Tumutan Tujuh”.
Tujuh sungai tersebut antara lain Sungai Padang Guci, Air Kinal, Air Bengkenang, Air Kendurang di Bengkulu, serta Sungai Lematang, Sungai Enim, dan Sungai Ogan di Sumatera Selatan.
Air dari sungai digunakan Suku Semende yang sebagian besar berkebun kopi, selain sebagai air bersih untuk dikonsumsi, mandi, mencuci, juga untuk persawahan.
Wilayah permukiman tertua Suku Semende berada di hulu Sungai Enim, Sungai Ogan, dan Sungai Lematang, yang dikenal sebagai “Semende Darat”, yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
“Mata air Sungai Enim berasal dari Bukit Bepagut melalui Aik Enim Kidaw dan Aik Enim Tengah. Sementara, mata air Sungai Ogan berasal dari Bukit Lumut Balai melalui Aik Ogan Kanan dan Aik Ogan Kiri. Dari Gunung Patah mengalir Aik Endikat, yang menjadi hulu dari Sungai Lematang,” kata Hasan Zen, tokoh masyarakat Suku Semende, awal Juli 2025.

Bagan sungai bagi Suku Semende terbagi dari mata air yang disebut mate aik, ranting sungai disebut luang, anak sungai disebut aik besak, serta sungai atau batang hari.
Selain dari sungai, sumber air juga berasal dari sejumlah tebat atau danau kecil. Beberapa tebat digunakan sebagai sumber air persawahan dan kebutuhan rumah tangga. Beberapa tebat yang cukup dikenal antara lain Tebat Dalam atau Tebat Puyang, Tebat Pelawi, Tebat Mandian, dan Tebat Bandes.
Sementara beberapa luang dan aik besak di sejumlah perbukitan seperti Bukit Lumut Balai, Bukit Bepagut, Bukit Balai, dan bukit kecil lainnya menghadirkan sejumlah air terjun.
Air terjun yang sudah diketahui antara lain Air Terjun Curup Tinggi dari Aik Udangan dan Air Terjun Kunyit dari Aik Udangan.
“Mungkin masih banyak air terjun di wilayah Semende Darat, tapi keberadaannya belum diketahui atau diberi nama,” kata Erfan Fahliansyah, pencinta alam yang menetap di Desa Palak Tanah, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pertengahan Juli 2025.
Beberapa jenis ikan yang hidup di sejumlah sungai tersebut, antara lain ikan semah (Tor tambroides), ikan cengkak (Xenentodon cancila), ikan pilok (Barbodes schwanenfeldii), ikan tilan (Mastacembelus armatus), dan ikan baung (Mystus nemurus). Semenrtara di tebat, masyarakat banyak memelihara ikan emas (Cyprinus carpio) dan ikan mujahir (Oreochromis mossambicus).

Aturan adat air
Guna menjaga keberlangsungan sungai dan mata air, Suku Semende membuat sejumlah aturan adat.
Pertama, masyarakat Suku Semende dilarang membangun rumah atau permukiman dekat sungai atau mata air. Gunanya, sumber air terjaga dari limbah atau kotoran dari rumah tangga.
“Guna mendapatkan air bersih, kami membuat sumur. Alternatifnya, kami menyalurkan air dari sungai ke rumah menggunakan bambu yang disambung, yang sekarang sebagian besar diganti pipa,” kata Dapawi, warga Desa Kota Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah.
Kedua, dilarang menebang pohon atau hutan di hulu atau sepanjang sungai dan mata airnya. Gunanya, agar sumber air terus terjaga dan tidak terjadi longsor.
Larangan ini membuat hutan di atas bukit yang menjadi hulu sungai tidak dirusak atau dibuka menjadi perkebunan. Bahkan, setiap perkebunan kopi wajib menyisakan satu hamparan kecil hutan yang disebut “jungut”. Gunanya, menjaga keberadaan air tanah dan rumah bagi sejumlah satwa.

Ketiga, dilarang mengambil batuan di sungai. Gunanya, agar badan sungai tidak mengalami pendangkalan atau abrasi.
“Selain untuk menjaga kualitas air, larangan membangun rumah atau permukiman dekat sungai atau mata air, juga bertujuan agar tidak berkonflik dengan satwa seperti harimau, yang juga membutuhkan air. Juga, terhindar bencana banjir dan longsor,” jelas Dapawi.
Saat ini, jika ada warga yang melanggar memang tidak mendapatkan sanksi seperti denda dan hukuman lain. Sebab, sejak pemerintahan marga dibubarkan dan diganti pemerintahan desa, hukum adat tidak lagi berlaku.
“Tapi secara sosial tetap ada sanksi. Salah satunya, didiamkan atau tidak dipedulikan oleh warga. Sehingga, mereka yang bersalah akan merasa diasingkan.”

Sumber air
Sejak kehadiran perusahaan geothermal atau PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), di Bukit Balai dan di Bukit Lumut Balai, sebagian besar masyarakat Suku Semende mencemaskan keberlanjutan air.
Sejumlah warga mengaku adanya kenaikan suhu udara, penurunan debit air, dan air sungai menjadi keruh, sehingga mengganggu produksi persawahan dan kebun kopi.
“Selama lima tahun terakhir, produksi kopi kami menurun. Meskipun harga kopi naik, tapi produksinya tidak seperti sepuluh tahun lalu. Apakah ini pengaruh aktivitas geothermal, kami tidak tahu, tapi itulah kondisinya,” kata Sehromli, warga Desa Muara Tenang, Kecamatan Semende Darat Tengah.
Dr. Rabin Ibnu Zainal dari Pilar Nusantara (PINUS), sebuah lembaga nonpemerintah yang melakukan pendampingan Perhutanan Sosial (PS) di Semende, mendapatkan sejumlah keluhan dari masyarakat terkait kondisi air di Semende. Misalnya debit air yang berkurang, serta air menjadi keruh dan berbau.
“Jadi perlu pengelolaan yang transparan dan partisipatif serta pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas panas bumi,” katanya.

Surya Darma, Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), kepada Mongabay Indonesia, Kamis (17/7/2025), menilai kecemasan akan krisis air untuk pertanian dan perkebunan akibat PLTP, tidak perlu berlebihan.
Pertama, PLTP sama sekali tidak menggunakan air permukaan sebagai sumber utama energinya. Fluida panas bumi yang menggerakkan turbin berasal dari reservoir di kedalaman ribuan meter di bawah tanah. Reservoir ini justru harus terisolasi dari air tanah dangkal untuk mencegah korosi pada peralatan pembangkit.
Kedua, kebutuhan air permukaan sangat terbatas dan hanya di fase awal. Air permukaan hanya dipakai dalam jumlah kecil saat pengeboran untuk lumpur bor. Setelah pengeboran usai, penggunaan air ini pun berhenti.
Ketiga, PLTP beroperasi dalam siklus tertutup. Uap panas bumi yang sudah menggerakkan turbin akan melewati menara pendingin (cooling tower) yang unik. Berbeda dengan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang butuh air permukaan untuk pendinginan, PLTP memanfaatkan udara dingin dan bersih sebagai media pendingin utamanya. Udara ini diisap masuk, mendinginkan kondensor, lalu diembuskan keluar melalui cerobong tinggi.
Air hasil kondensasi uap panas bumi, bersama dengan brine (cairan panas bumi yang terpisah), akan diinjeksikan kembali ke perut bumi untuk memelihara reservoir. Sesekali, memang diperlukan penambahan air dari luar untuk menjaga volume reservoir, yang bisa diambil dari air permukaan atau bahkan limbah rumah tangga atau perkotaan yang sudah diolah.
“Artinya, operasional PLTP nyaris tidak menggunakan air permukaan. Justru, kelangsungan hutan yang terjaga akan mendukung keberlanjutan pasokan air alami yang sangat penting bagi pertanian dan perkebunan di Semende. Proyek panas bumi memiliki kepentingan besar dalam menjaga kelestarian hutan untuk jangka panjang,” tuturnya.
*****
Kearifan Suku Semende: Menjaga Alam dan Bersahabat dengan Kucing Liar