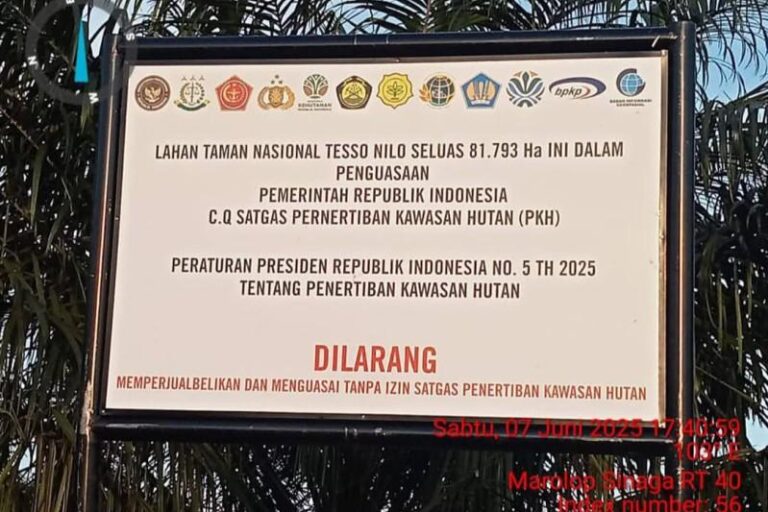- Tambang nikel yang menggerogoti pulau-pulau kecil di nusantara ini, seperti Raja Ampat, Papua Barat Daya, menuai reaksi keras dari tokoh-tokoh agama. Mereka menyerukan cabut izin-izin tambang di pulau kecil apalagi sudah jelas-jelas melanggar aturan. Sebelumnya, kritik muncul ketika pemerintah lewat Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) memperbolehkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola tambang.
- Roy Murtadho, pengasuh pesantren ekologi Misykat Al-Anwar mengatakan, industri ekstraktif itu bersifat merusak lingkungan di darat maupun laut. Tambang juga menimbulkan konflik sosial, terutama dengan masyarakat pulau yang mengandalkan laut sebagai mata pencaharian.
- Hening Parlan, Direktur Green Faith Indonesia, mengatakan, pertambangan di pulau-pulau kecil mempercepat kehancuran ekosistem dan memperparah krisis iklim. Untuk itu, jangan hanya mencabut izin tambang di Raja Ampat, juga seluruh pulau kecil dan mengevaluasi kembali izin tambang lainnya.
- Pendeta Binsar Pakpahan, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (STFT Jakarta) menyebut, eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta hasil keserakahan struktural yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Tambang nikel yang menggerogoti pulau-pulau kecil di nusantara ini, seperti Raja Ampat, Papua Barat Daya, menuai reaksi keras dari tokoh-tokoh agama. Mereka menyerukan cabut izin-izin tambang di pulau kecil apalagi sudah jelas-jelang melanggar aturan. Sebelumnya, kritik muncul ketika pemerintah lewat Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) memperbolehkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola tambang.
Roy Murtadho, pengasuh pesantren ekologi Misykat Al-Anwar mengatakan, industri ekstraktif itu bersifat merusak lingkungan di darat maupun laut. Tambang juga menimbulkan konflik sosial, terutama dengan masyarakat pulau yang mengandalkan laut sebagai mata pencaharian.
Tokoh pemuda Nahdlatul Ulama (NU) ini menegaskan, jelas ada larangan menambang di pulau kecil. UU Nomor 1/2014 tentang Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Lalu ,makin kuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 tegas melarang penambang di pulau kurang dari 2.000 km.²
Roy juga mengkritik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang justru mendukung tambang, bahkan ada yang jadi bagian dalam jajaran direksi perusahaan tambang di Pulau Gag.
Ahmad Fahrur Rozi, selaku pengurus PBNU bidang keagamaan, misal, menjabat sebagai komisaris PT Gag Nikel.
“Sangat mengecewakan betul karena PBNU nggak punya sikap tegas terhadap berlangsungnya ekstraktivisme di pulau-pulau kecil,” katanya kepada Mongabay, medio Juni lalu.
Bahkan, Ulil Abshar Abdalla, Ketua Lakspedam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dalam obrolan bersama Iqbal Damanik Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia di Kompas TV, menganalogikan kelompok pegiat lingkungan pemprotes tambang sebagai Wahabi Lingkungan. Dia bilang, Wahabisme artinya menjaga kemurnian ajaran hingga tak boleh tersentuh.
“Saya lihat teman-teman aktivis lebih puritan, lebih ekstrem. Seakan-akan menolak total pertambangan.”
Roy bilang, bila PBNU mengklaim cinta tanah air seharusnya bersikap adil serta sejalan dengan regulasi, bahwa tambang di Pulau kecil memang melanggar.
“Jadi itu (PBNU) mengecewakan, tapi kami nggak heran PBNU nggak punya sikap karena emang ada petingginya yang terlibat di sana,” katanya.
Dia juga mengkritik Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Ahmad Fahrur Rozi yang mengatakan, aktivitas tambang PT Gag Nikel tidak merusak pulau karena berada jauh dari kawasan konservasi Raja Ampat.
Pernyataan itu, katanya, membuktikan mereka tak mengerti konsep ekosistem.
“Mereka nggak paham konsep ekosistem sebagai satu kesatuan sistem kompleks yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup (biotik) dan lingkungannya (abiotik) di suatu kawasan tertentu.”
Keberadaan tambang justru berdampak pada keseluruhan Raja Ampat. Kerusakan lingkungan juga akan mempengaruhi sektor perikanan dan pariwisata yang menjadi andalan daerah berjuluk surga terakhir itu.
“Mestinya keterlibatan NU di pemerintah itu yang kritis. Bukan malah mendukung atau diam saja.”
Setelah ramai kampanye penolakan tambang nikel di Raja Ampat, yang berawal dari aksi Greenpeace, pemerintah mencabut empat izin tetapi tetap mempertahankan PT Gag Nikel.

Cabut izin-izin tambang di pulau kecil
Tak hanya empat izin tambang nikel, tokoh agama maupun tokoh muda organisasi keagamaan mendesak pemerintah mencabut semua izin tambang pulau-pulau kecil.
Laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), terdapat 195 izin pertambangan dengan luas konsesi 351.933 hektar mencaplok 35 pulau kecil di Indonesia.
“Harus dicabut atas nama penegakan hukum dan kelestarian lingkungan. Harusnya dibatalkan (izinnya),” kata Roy.
Dia contohkan kerusakan di Pulau Kabaena dan Wawonii karena tambang nikel, namun pemerintah seakan diam dan membiarkan.
“Kalau bahasa filsafatnya itu kontradiksi interminus. Masa’ dia (pemerintah) bikin Undang-undang, dia sendiri yang melanggar.”
Pulau-pulau kecil mestinya terlindungi dan jadi tanggung jawab bersama agar ekosistem tetap lestari. Pemerintah daerah dan pusat, katanya, harus mematuhi aturan tentang pulau-pulau kecil.
Senada dengan Hening Parlan, Direktur Green Faith Indonesia, organisasi jaringan Muhammadiyah yang fokus pada isu lingkungan. Dia mengatakan, pertambangan di pulau-pulau kecil mempercepat kehancuran ekosistem dan memperparah krisis iklim. Untuk itu, jangan hanya mencabut izin tambang di Raja Ampat, juga seluruh pulau kecil dan mengevaluasi kembali izin tambang lainnya.
Sebagai negara kepulauan, bangsa Indonesia memiliki amanah spiritual dan konstitusional untuk menjaga lebih dari 10.000 pulau kecil.
Dia bilang, ambisi mengembangkan kendaraan listrik berdalih transisi energi justru membawa kehancuran. Nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik, kata Hening, menambah penderitaan rakyat dan kerusakan alam.
Data Forest Watch Indonesia menyebutkan, 5.700 hektar hutan hilang Maluku Utara hilang sejak 2021 dampak tambang.
Studi Nexus Foundation Juli 2024 menemukan, logam berat berbahaya merkuri dan arsenik di tubuh ikan dan darah warga Teluk Weda. Bahkan, kadar logam berat di tubuh warga lebih tinggi dari pekerja industri.
“Ini bentuk ketidakadilan ekologis,” kata Hening.
Kondisi kesehatan warga memburuk. Kasus ISPA melonjak dari 434 pada 2020 menjadi 10.579 kasus pada 2023, ditambah 500 kasus diare per tahun.
“Transisi energi seharusnya selaras dengan nilai keadilan ekologis, bukan menciptakan kezaliman baru atas nama kemajuan.”
Parid Ridwanuddin, manajer program Green Faith mengatakan, saat ini bumi menghadapi triple planetary crisis, yakni krisis iklim, polusi dan keterancaman keanekaragaman hayati. Hal itu terpicu sejarah panjang industri ekstraktif yang memproduksi banyak emisi racun.
Begitu pula pertambangan di pulau kecil yang berbahaya dan mengakibatkan situasi menjadi tidak normal. “Artinya, akan semakin banyak bencana.”
Pemulihan lingkungan yang terdampak tambang akan sulit dan perlu waktu lama.
“Ini kehancuran ekologis dalam jangka panjang. Saya sering menyebutnya sebagai bom waktu. Cara menyelamatkan adalah jangan ditambang,” katanya.
Kendati demikian, kata Parid, watak ekonomi Pemerintah Indonesia tak memandang kehancuran sebagai bencana. Hal itulah yang menyebabkan, pemerintah enggan mencabut izin-izin tambang di pulau kecil.
Pencabutan empat izin tambang nikel di Raja Ampat pun terjadi ketika viral, mendapat perhatian masyarakat luas.
Konflik kepentingan dan ekonomi politik juga menghambat. Pejabat, politikus dan aparat menjadi tameng para investor tambang.
“Maka, jangan aneh, misal di Wawonii sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, izin belum cabut. Saya kira di dalam banyak hal-hal penting di dalamnya urusan politik. Ada keterkaitan antara aktor-aktor tambang ini dengan aktor-aktor ekonomi politik di Indonesia. Jangan harap pemerintah ini bisa tegas.”

Kekerasan pada alam dan manusia
Uskup Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru OSA, mengecam aktivitas tambang nikel sebagai bentuk kekerasan terhadap alam dan masyarakat Papua. Dia menyebut itu sebagai bagian dari ketamakan oligarki yang menghancurkan keharmonisan antara manusia dan ciptaan Tuhan.
“Perasaan saya tercabik-cabik. Raja Ampat yang selama ini dimuliakan sebagai mahakarya ciptaan Tuhan, kini dilukai oleh kerakusan manusia,” katanya dalam khotbah Misa Hari Raya Pentakosta 8 Juni lalu di Gereja Katedral Tiga Raja, Timika, Papua Tengah.
Dia bilang, ambisi, ketamakan dan kerakusan mengeksploitasi sumber daya alam di Papua menciptakan konflik. “Raja empat yang indah mulai hancur karena ketamakan dan kerakusan oligarki dan penguasa dengan slogan demi proyek strategis nasional.”
Pendeta Binsar Pakpahan, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (STFT Jakarta) menyebut, eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta hasil keserakahan struktural yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Dia pun mengajak umat beragama menyuarakan perlawanan terhadap sistem yang menormalisasi perusakan lingkungan Gerakan hidup ugahari atau hidup cukup dan sederhana harus menjangkau dunia korporasi dan pengambil kebijakan.
“Tuhan menciptakan bumi ini sebagai rumah bersama, bukan sebagai ladang eksploitasi. Ketika keserakahan mengambil alih nurani, maka umat beriman wajib berdiri membela ciptaan,” katanya.
Romo Ferry Sutrisna Widjaja, Imam Katolik yang bekerja di Eco Camp Bandung mengingat soal pertanyaan mendalam mendiang Paus Fransiskus dalam Laudato Si.
Kala itu Paus bertanya kondisi kerusakan alam yang akan jadi ‘warisan’ generasi mendatang.
“Apakah hati kita masih bisa mendengarkan jeritan alam yang dirusak dan jeritan masyarakat lokal yang dirugikan oleh eksploitasi pertambangan ekstraktif di pulau-pulau kecil?” katanya.
Kecaman soal aktivitas tambang merusak alam juga datang dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI). PGI menilai, industri ekstraktif meluas di Indonesia mengabaikan keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan martabat kemanusiaan.
Krisis ekologis, katanya, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan ketidakadilan terhadap masyarakat lokal/ adat yang kehilangan ruang hidup.

Pendeta Darwin Darmawan, Sekretaris Umum PGI mengajak masyarakat melawan keserakahan oligarki yang melakukan eksploitasi alam berlebihan, serta menolak praktik-praktik destruktif terhadap ciptaan-Nya.
“Apa yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan praktik-praktik eksploitasi sumber daya atas nama hilirisasi, namun berlangsung secara destruktif, tanpa visi pemulihan, penciptaan keadilan, dan pertimbangan moral-spiritualitas ekologis.”
Darwin menyadari, praktik ekstraktif tak hanya terjadi di Raja Ampat juga Indonesia bagian lain, dari Barat sampai Timur.
PGI menentang teologi antroposentris tentang alam. Manusia bukan pusat dan pemilik mutlak alam, tetapi bagian dari alam. Alam jadi rumah bersama dengan makhluk hidup lain.
“Manusia bukan tuan atas alam, melainkan sahabat penatalayan yang wajib merawat dan mendukung keseimbangan ekologis demi keberlangsungan hidup semua makhluk di bumi,” katanya.
Hal senada Putu Ardana, Masyarakat Adat Dalem Tamblingan Bali, sampaikan. Dia bilang, keimanan masyarakat adat itu disebut piagem gama tirta yang memuliakan air dan menjaga harmoni dengan alam.
“Lokasi -lokasi pegunungan dan masyarakat adat di berbagai wilayah tanah air termasuk di Raja Ampat pasti memiliki kearifan lokal dalam menjaga bumi. Kemudian rusak karena industri,” katanya
Upasaka Titha Sukho dari Pengerak Peduli Generasi Agama Budha menyampaikan, merusak hutan tempat tinggal para makhluk berarti menentang dharma dan menanam benih penderitaan atau karma buruk. Merusak hutan, katanya, sama saja menghancurkan tempat tinggal dan tempat mencari makan untuk hidup.
*****