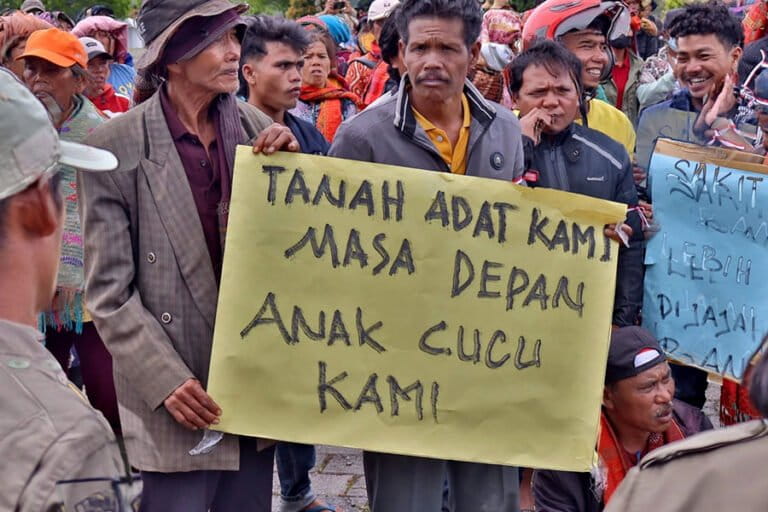- Kura-kura byuku (Orlitia Borneensis) merupakan satwa dilindungi dan masuk CITES Appendix II.
- Nama lokal kura-kura ini adalah bajuku. Dalam Bahasa Inggris disebut Malaysia Giant Turtle, meski penyebarannya meliputi Malaysia dan juga Indonesia.
- Byuku adalah keajaiban evolusi. Ia termasuk keluarga Geoemydidae, kelompok kura-kura air tawar yang telah bertahan jutaan tahun di ekosistem lahan basah tropis Asia Tenggara.
- Keunikan fisiologisnya membuatnya mampu hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah dan tingkat keasaman tinggi, seperti di rawa gambut. Dalam ekosistemnya, byuku berperan sebagai penjaga keseimbangan. Ia membantu menjaga kualitas air dengan memangsa hewan-hewan kecil yang berlebih, sekaligus pemakan bangkai. Ia juga menyebarkan biji tumbuhan air melalui pergerakannya di dasar rawa.
Tempurung byuku yang selebar perisai, bisa menutupi badan orang dewasa. Ukuran ini benar-benar luar biasa untuk seekor kura-kura. Jika dibandingkan dengan bulus yang umum menghuni perairan di Pulau Jawa, tempurung byuku bisa dua kali lebih besar. Panjangnya mencapai 80 sentimeter, sementara bulus jarang lebih dari 50 sentimeter.
Bukan hanya besar, tempurung byuku juga keras dan kokoh. Tameng hidup yang melindunginya dari serangan burung pemangsa, biawak, hingga buaya. Warna tempurungnya cokelat, hingga hijau kehitaman, berpadu dengan tubuh berlumpur yang membuatnya seolah menyatu dengan dasar sungai atau rawa tempat ia bersembunyi.
Namun, tempurung sebesar itu tak cukup kuat melindunginya dari ancaman terbesar yang datang, yaitu manusia.
“Kura-kura ini merupakan satwa dilindungi dan masuk CITES Appendix II,” ungkap Herdhanu Jayanto, peneliti konservasi satwa Yayasan Konklusi di Yogyakarta, kepada Mongabay Indonesia, Jumat (17/10/2025).
Status konservasinya Critically Endangered atau Kritis, akibat penurunan populasi lebih dari 80 persen selama tiga generasi. “Titik puncaknya terjadi 1990-an, saat perburuan dan perdagangan kura-kura untuk ekspor berlangsung masif.”

Byuku adalah keajaiban evolusi. Ia termasuk keluarga Geoemydidae, kelompok kura-kura air tawar yang telah bertahan jutaan tahun di ekosistem lahan basah tropis Asia Tenggara.
Keunikan fisiologisnya membuatnya mampu hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah dan tingkat keasaman tinggi, seperti di rawa gambut. Dalam ekosistemnya, byuku berperan sebagai penjaga keseimbangan. Ia membantu menjaga kualitas air dengan memangsa hewan-hewan kecil yang berlebih, sekaligus pemakan bangkai. Ia juga menyebarkan biji tumbuhan air melalui pergerakannya di dasar rawa.
Laporan asesmen IUCN Red List menyebutkan bahwa byuku banyak diperdagangkan di pasar makanan dan obat tradisional di Asia Tenggara serta China.
“Hewan ini diburu atau dipelihara, dipotong, dan dijual secara ilegal untuk memenuhi permintaan daging eksotik dan bahan obat.”
Ancaman tak hanya datang dari meja makan. Rawa dan sungai tempat byuku mencari makan telah berubah menjadi kebun sawit. Perlahan ruang hidupnya pun menghilang.
“Populasi mereka tidak terpantau namun diperkirakan terus menurun, khususnya karena hilangnya habitat akibat konversi lahan dan menurunnya kualitas perairan tawar di Sumatera dan Kalimantan,” tambah Herdhanu. “Nasib nahas bagi jenis Geoemydidae terbesar di dunia.”

Penyelamatan
Nama lokal lain kura-kura ini adalah bajuku. Dalam Bahasa Inggris disebut Malaysia Giant Turtle, meski penyebarannya meliputi Malaysia dan juga Indonesia. Nama ilmiahnya Orlitia Borneensis, namun kura-kura ini tak hanya ditemukan di Kalimantan. Ada pula di semenanjung Malaysia, Sumatera, Bangka Belitung. Bahkan, dulu pernah tersebar hingga Thailand dan Pulau Jawa.
“Di Jawa, diperkirakan jenis ini hidup di sungai wilayah Sambungmacan, Sragen, Jawa Tengah hingga pertengahan pleistosen berdasarkan bukti fosilnya,” papar co-founder dan manajer program di Konklusi ini.
Melestarikan byuku bukan pekara sederhana. Spesies ini hidup tersembunyi, lambat berkembang biak, dan habitatnya terpecah di wilayah rawa yang kian sempit.
Menurutnya, penyelamatan harus dilakukan dari dua arah. Pemerintah menegakkan regulasi, memperkuat pengawasan atas penggunaan lahan, menolak deforestasi, serta memperbaiki ekosistem perairan. Sementara, masyarakat bisa mulai mengidentifikasi jenis-jenis satwa air yang dulu mudah ditemui dan kini makin jarang.
“Di Yogyakarta, kami Yayasan Konklusi, Wildlife Recue Center Yogyakarta, Gembira Loka Zoo, dan BKSDA Yogyakarta melakukan upaya konservasi kolaboratif menggunakan pendekatan one-plan. Yaitu, menyelaraskan upaya ex situ dan in situ. Kami memulai dengan membuat koloni jaminan dari individu hasil penyelamatan BKSDA Yogyakarta.”

Koloni jaminan adalah populasi spesies yang dipelihara di luar habitat alami, untuk mencegah kepunahan dan mendukung kelangsungan spesies yang terancam. Tujuannya, untuk menjaga cadangan individu sehat secara fisik dan genetik, yang dapat digunakan untuk reintroduksi ke alam atau memperkuat populasi liar jika habitat alami rusak.
“Konsep ini mirip dengan yang dilakukan pada badak jawa, katak merah, atau kura-kura rote,” jelas Herdhanu. “Kami juga sedang melakukan pemetaan genetika individu yang kami pelihara, agar bisa menentukan pasangan induk terbaik dan mengetahui lokalitas asalnya. Data ini akan sangat penting jika suatu saat kami melakukan translokasi atau reintroduksi.”
Awal Juli lalu mereka pergi ke beberapa kota di Kalimantan, untuk mengumpulkan sampel darah dan usap kloaka byuku. Konservasi in situ dikerjakan di Tebat Rasau, Bangka Belitung. Sementara konservasi ex situ di kebun binatang Gembira Loka, Yogyakarta.
Upaya semacam ini bukan melulu mengerjakan hal-hal teknis, tetapi juga simbol harapan bahwa manusia masih bisa memperbaiki kesalahan masa lalu. Setidaknya, untuk satu spesies yang telah banyak kehilangan ruang hidupnya.

Habitat sungai
Hubungan manusia dengan sungai kini kian renggang. Padahal, sungai adalah nadi peradaban, tempat manusia belajar membaca arah air dan memahami siklus kehidupan.
“Sungai bukan cuma badan air,” kata Herdhanu. “Tapi tempat dan sumber kehidupan, ruang memori, dan warisan budaya yang diyakini turun-temurun oleh masyarakat sekitarnya.”
Sayangnya, gangguan ekosistem perairan tawar datang dari berbagai arah. Sungai kemudian berubah menjadi saluran pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Dulu menjadi rumah bagi aneka reptil air, kini tercemar dan kehilangan konektivitas ekosistemnya.
Sungai Boyong-Code yang membelah Kota Yogyakarta, misalnya, yang melewati permukiman kumuh harus berhadapan dengan kebiasaan warga membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai. Meski kini dua hal ini jauh berkurang berkat program Mundhur, Munggah, Madhep Kali (memundurkan dan menaikkan rumah di sepanjang talud sungai, serta menjadikan sungai sebagai halaman depan).
Belum lagi gangguan dari spesies invasif. Survei yayasan ini yang dilakukan pada 2012 bahkan menemukan keberadaan bullfrog (Lithobates catesbeianus) dan kura-kura brazil (Trachemys scripta elegans), spesies invasif yang kemungkinan besar berasal dari hewan peliharaan yang dilepaskan ke alam.
Namun, secara umum pembangunan infrastruktur sungai di Indonesia sering kali tidak memperhatikan keberadaan satwa air.
“Contohnya bendungan atau dam,” jelas Herdhanu. “Struktur itu memang mengendalikan sedimentasi, tapi juga menjadi penghalang bagi migrasi satwa air. Kondisi ini memprihatinkan dari sudut pandang fungsi dan jasa ekosistem, sehingga tidak aneh jika banyak jenis satwa mulai langka dan hilang.”

Akibatnya, jenis-jenis reptil yang dulu bisa ditemui umum kini mulai menghilang. Hanya spesies yang memiliki toleransi tinggi terhadap gangguan manusia yang mampu bertahan.
“Bulus (Amyda cartilagenea), sebenarnya cukup resilience,” kata lulusan Fakultas Biologi UGM ini. Tapi tanpa kualitas habitat yang baik, sulit bagi spesies semacam bulus maupun byuku untuk bertahan di sungai urban.
Namun, dia percaya ekosistem sungai bisa dipulihkan. Contoh keberhasilan restorasi datang dari luar negeri. Chenggyecheon Stream di Korea Selatan, atau proyek Sponge City di China. Di Indonesia, taman kota seperti Tebet Eco Park menjadi bukti bahwa ruang hijau bisa hidup berdampingan dengan aktivitas manusia jika dirancang dengan visi ekologis jangka panjang.
Kota Yogyakarta bisa menirunya. Dengan dana keistimewaannya, bisa saja dibangun kantong-kantong hijau kecil di sekitar Boyong dan Code untuk menghidupkan kembali biodiversitas air.
Habitat air tawar seperti sungai dan rawa bukan sekadar genangan air yang sepi. Tempat itu adalah nadi kehidupan, penyimpan karbon, penjaga air tanah, dan rumah bagi ratusan makhluk yang tak selalu terlihat. Ketika sungai dan rawa hilang, bukan hanya bulus atau byuku yang pergi, tapi juga keseimbangan yang menopang kehidupan manusia.
*****